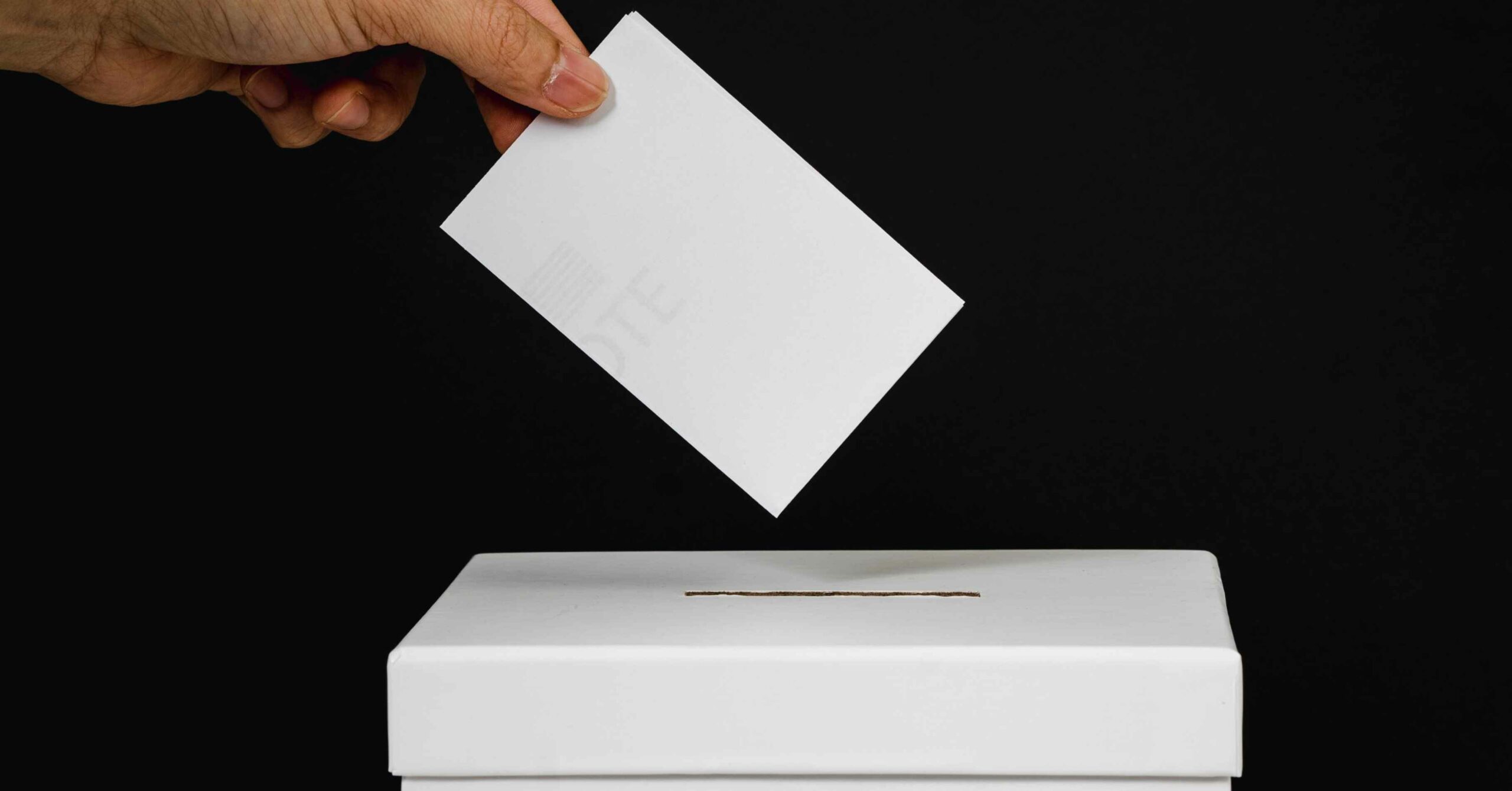Dua Dekade Desentralisasi: Seberapa Sering Sih Suara Kita Didengar?
Sejak menghirup segar udara reformasi, kebijakan dalam negeri Indonesia berubah banyak. Dari yang semula terpusat di era Orde Baru, Indonesia mulai menerapkan pola desentralisasi di era reformasi. Dinamai Otonomi Daerah, pola ini diharapkan bisa melibatkan partisipasi publik sehingga produk kebijakan yang lahir di daerah mampu menjawab tantangan masyarakat.
Regulasi mengenai hal ini sudah disahkan sejak 1999. Ruangnya semakin besar seiring perkembangan regulasi. Pada 2008, bahkan lahir UU Keterbukaan Informasi yang mengharuskan pemerintah membuka informasi apapun yang bisa diakses oleh publik.
Tapi lebih dari dua puluh tahun berselang, sejauh mana sih suara kita didengar pemerintah?
Peneliti CSIS Arya Fernandez tak menampik kalau dalam dua puluh tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan dalam pelibatan aspirasi publik pada penyusunan kebijakan. Hal ini juga dirasakan dari sisi peningkatan kesejahteraan publik, peningkatan tata kelola pemerintah daerah, dan inisiatif serta inovasi baik dari pemerintah daerah.
Namun, di sisi lain, daerah juga menghadapi situasi rumit dengan fakta meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Mengacu pada data KPK, tingkat korupsi di daerah tertinggi terjadi pada rentang 2016 ke 2018. Kasus yang paling banyak terkait penyuapan dan pengadaan barang dan jasa.
“Di tengah capaian baik di berbagai tempat memang ada juga kendala-kendala terkait korupsi tadi,” kata Arya dalam diskusi daring yang dihelat Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Rabu (14/4/2021).
Belum lagi soal dinasti politik yang menguat dan juga soal kinerja anggota dewan dan eksekutif daerah yang belum baik secara merata.
Menurut Arya, masyarakat sebetulnya berhak berpartisipasi dalam Perda dan Rancangan Pembangunan Daerah. Dan ini diatur secara nasional baik dalam Musrembang atau penerapan e-government. Namun, dari data yang dia lihat di lapangan, Arya mengaku sangsi apakah betul masyarakat dilibatkan dalam penyusunan suatu kebijakan.
“Regulasinya ada, operasionalisasinya ada, tapi dari policy cycle-nya dari perencanaan, perumusan, konsultasi publik, sampai proses pengundangan, saya kok enggak begitu yakin partisipasi publik itu diakomodasi baik,” kata Arya.
Arya menilai, selama ini pengambilan keputusan lebih banyak berbasis pada elite. Itu hanya menjadi proses politik yang diputuskan secara bersama oleh dewan dan pemerintah yang justru jarang sekali melibatkan masyarakat.
“Partisipasinya semu saja dan bahkan formalitas. Memang ada contoh baiknya di masyarakat, seperti UU Desa. Tapi banyak kebijakan di daerah itu umumnya hasil kesepakatan politik antara dewan dan kepala daerah,” ucap dia.
Senada dengan Arya, analis kebijakan KPPOD, Eduardo Edwin menyebut semakin hari pelibatan masyarakat memang dijamin oleh UU. Tetapi untuk output-nya belum begitu memuaskan. Berdasarkan data KPPOD, ada 347 perda bermasalah yang salah satu alasan determinannya, karena minimnya partisipasi publik.
Dia menyebut dalam negara demokrasi, partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dibagi pada tiga derajat. Yakni partispasi palsu, partisipasi parsial atau setengah-setengah, dan partisipasi penuh. Untuk yang terakhir, ini bisa terjadi saat masyarakat dari berbagai golongan punya peran yang sama untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan.
“Sehingga nantinya Kebijakan publik yang muncul berbasis pada persoalan yang terjadi di masyatrakat. Sehingga menciptakan gol otonomi daerah yakni kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.
Dia pun menilai ada sejumlah catatan yang menjadi tantangan di lapangan dan perlu diperbaiki. Yang pertama adalah ketiadaan regulasi yang sifatnya punishment and reward. Dengan ketiadaan regulasi ini maka partisipasi masyarakat baik jika dilaksanakan tapi tidak mengapa jika ditinggalkan.
“Padahal utnuk mencapai partisipasi penuh harus ada dorongan yang menuntut pemerintah. Harus ada regulasi yang membuat daya paksa agar pemerintah ikut,” kata Edwin.
Selain itu adalah platform. Mungkin Jakarta sudah punya saluran terpadu untuk menjaring aspirasi publik. Tapi bagaimana dengan daerah lain? “Praktik baik ini perlu ditularkan. Cara menelurkannya harus ada daya paksa tadi,” ucap dia seraya menambahkan daerah juga bisa menjaring partisipasi publik lewat forum-forum adat.
Dia juga tak menampik kalau saat ini partisipasi masih terbatas di kalangan yang punya akses. Baik itu NGO atau Mahasiswa. “Tapi apakabar kesadaran masyarakat secara luas? Partisipasi mereka harus terangkat juga. Ini sosialisasi harus sampai ke level tersebut. Ini perlu jadi refleksi bernegara selanjutnya,” ujar dia.
Adapun yang terakhir harus ada porsi yang setara saat berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan. “Harus ada porsi setara sehingga partisipasi yang melahirkan ruang dialektika agar menghasilkan kebijakan yang sehat,” ucap Edwin.