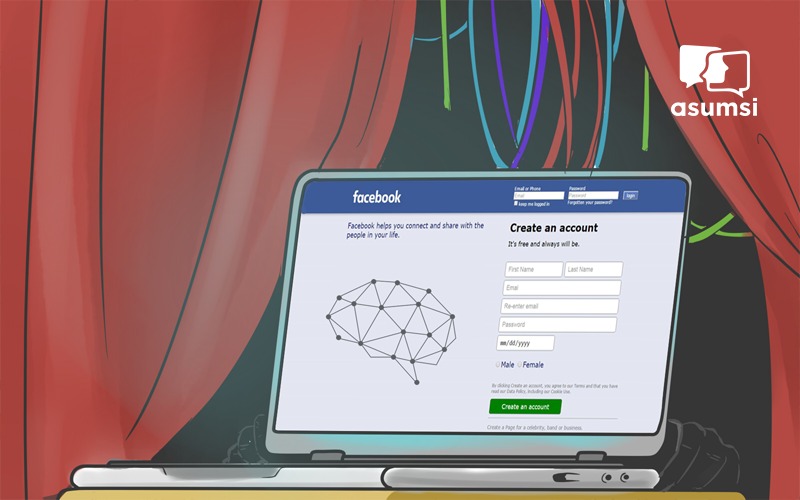Bagaimana Cambridge Analytica Mengatur Pilihan Kita
Informasi mengenai Cambridge Analytica kembali mencuat setelah Netflix merilis film dokumenter terbarunya berjudul The Great Hack pada akhir Juli lalu. Mengapa Cambridge Analytica, yang jauh di New York, Washington, dan London, begitu penting untuk diketahui dunia? Apa yang telah dikerjakannya?
Christopher Wylie, mantan analis data Cambridge Analytica sendiri memantik tegas bagaimana publik semestinya memandang firma tersebut. “Salah bila menyebut Cambridge Analytica sebagai perusahaan murni ilmu data atau algoritma. Ini adalah mesin propaganda layanan lengkap,” tukasnya dalam The Great Hack.
Wylie, bersama jurnalis investigatif The Guardian Carole Cadwalladr, merujuk pemilu Amerika Serikat mutakhir sebagai contoh. Pada 2016, Donald Trump berhasil mengalahkan Hillary Clinton dengan kemenangan elektoral 304 berbanding 227. Ini adalah hasil yang umumnya tak dapat diprediksi oleh berbagai lembaga survei dan konsultan politik di Amerika Serikat.
Cambridge Analytica disebut The Guardian sebagai otak di balik berbagai strategi politik Trump. Firma itu juga dihubung-hubungkan dengan induknya, SCL (Strategic Communication Laboratories) Group, yang sudah berdiri sejak 1990 dan banyak membantu dalam urusan menghimpun serta mengolah data.
Penelusuran skandal ini mulanya lahir berkat laporan Harry Davies di The Guardian pada Desember 2015. Dalam laporan tersebut, Davies menulis bahwa seorang senator di Amerika Serikat, Ted Cruz, telah memanfaatkan data pengguna Facebook untuk kepentingan iklan politiknya. Bagi Davies, cara itu bermasalah karena pemanfaatan data dilakukan tanpa kesepakatan pengguna.
Dalam laporan investigasinya tentang Brexit di tahun 2017, Cadwalladr merinci bagaimana keputusan politis negeri Ratu Elizabeth itu juga telah dipengaruhi iklan dan siasat politik yang tidak disadari masyarakatnya. Cadwalladr menyebut bahwa sistem demokrasi di negaranya telah dibajak.
Cadwalladr juga menyorot bagaimana cara kerja kampanye “Leave.EU” yang digagas Cambridge Analytica telah mempengaruhi perilaku politik masyarakat Inggris, lagi-lagi dengan memanfaatkan data di jagad maya. Hasil kampanye tersebut berbuah pada kemenangan 51,89% pemilih yang menuntut Inggris lepas dari Uni Eropa dalam referendum yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016.
Saat laporannya diterbitkan, Cadwalladr mendapat serangan karena dianggap menyiarkan berita palsu. Namun, ia tidak seketika berhenti. Cadwalladr berusaha mendapatkan informasi dari orang dalam Cambridge Analytica untuk mendukung hasil penemuannya. Dalam perjalanannya, ia pun bertemu dengan Wylie dan Brittany Kaiser yang telah mundur dari firma itu.
Wylie, yang dulu bekerja di Cambridge Analytica sebagai data analis, mengungkap sejumlah cara yang dilakukan firma tersebut dalam mengolah data yang dihimpun. Kaiser juga ikut menjelaskan keterlibatannya dalam kampanye Leave.EU, kemenangan Trump, dan bahkan membeberkan peran Facebook saat itu. Kaiser mengaku, akhirnya ia sadar bahwa cara kerja yang dilakukannya selama ini telah melanggar hak asasi manusia.
Pelanggaran data pribadi yang dilakukan perusahaan teknologi ini juga disadari oleh David Carrol, seorang pengajar dari Parsons School of Design di kota New York. Sebagai akademisi, ia sadar bahwa tingkah lakunya (juga sebagian besar orang di Amerika Serikat) sedang diprediksi dan digambarkan secara akurat. Ia kemudian menuntut Cambridge Analytica untuk mengembalikan data pribadinya yang telah diambil dari media sosial. Dalam tuntutannya, Carrol meminta Cambridge Analytica serta Facebook untuk menjelaskan: dari mana mereka mengambil data, bagaimana mereka memprosesnya, kepada siapa data tersebut dibagikan, dan apakah lumrah saja jika para pengguna tak diminta berpartisipasi dalam penyebaran data ini?
Menurut laporan The Guardian dan The New York Times, Facebook telah meloloskan sekitar 87 juta data pengguna tanpa persetujuan. Hal itu pula yang membuat Facebook mendapat denda US$5 miliar (Rp70 triliun) dari Federal Trade Commission (FTC) pada Juli 2019 karena terbukti melanggar privasi penggunanya.
Kilas Balik Cambridge Analytica
Pengadilan federal menunjukkan bahwa pelanggaran Facebook melibatkan Cambridge Analytica, yang menjadikan data sebagai alat mencapai tujuan politis kliennya. Data adalah komoditas baru. Brittany Kaiser, mantan direktur bisnis firma tersebut, mengatakan bahwa nilai data melampaui harga minyak jika dinominalkan.
Cambridge Analytica berasal dari sebuah perusahaan bernama SCL (Strategic Communication Laboratories) Group yang berdiri pada 1990. Dalam lansiran Bloomberg, SCL bermula hadir dengan nama Behavioural Dynamic Institute (BDI) yang diprakarsai Nigel Oakes, seseorang yang banyak bernaung pada produksi tayangan televisi dan periklanan.
Saat itu, Oakes merasa bahwa metode periklanan tradisional sudah kurang relevan. Maka kemudian ia menggaet psikolog dan antropolog untuk melihat cara baru dalam membentuk opini massa. Studi dan riset terus berlanjut karena dianggap membawa kemajuan. Hingga pada pertengahan 1993 SCL dicanangkan sebagai sebuah perusahaan mapan. Ia menggantikan BDI yang berubah konsep menjadi nirlaba.
SCL mulanya dikenal sebagai perusahaan yang berfokus pada riset perilaku dan strategi komunikasi. Dalam laman daringnya, ada tajuk “global election management agency“ yang kemudian menunjukkan bahwa mereka terang-terangan siap membantu kandidat politik untuk memenangkan pemilihan umum.
Baru pada 2013, Oakes bersama Alexander Nix, salah satu direktur SCL terlama, membentuk Cambridge Analytica untuk menyasar pasar yang lebih luas. Nix kemudian ditunjuk menjadi CEO pertama firma tersebut. Dilansir Campaign, selama sembilan tahun masa baktinya, Nix telah berhasil menangani 40 kampanye politik di AS, Karibia, Eropa, Afrika, dan Asia.
Nix secara sederhana mengungkapkan bagaimana Cambridge Analytica bekerja. “Karena kepribadian akan mendorong perilaku, lalu perilaku yang akan memengaruhi caramu memilih,” katanya. Brittany Kaiser juga menambahkan bahwa mereka mengambil setidaknya 4.000-5.000 titik data yang merepresentasikan setiap pengguna.
Data tersebut bisa diambil dari Facebook dengan berbagai rincian. Mulai dari daftar pertemanan, kapan berulang tahun, halaman yang disukai, hingga setiap huruf yang dimuat dalam status. Setiap detail yang terhimpun dalam Facebook dapat menjadi data yang jika dikomparasikan dengan ribuan data milik pengguna lain akan membentuk sebuah kecenderungan tertentu.
Bermodal gambaran itu, Cambridge Analytica akan menyajikan konten yang spesifik dan sesuai dengan preferensi pengguna. Konten yang disajikan bisa berupa iklan, video, dan berita. Semuanya dibalut dengan kepentingan klien untuk menarik suara pemilih. Semisal dalam The Great Hack, contoh konten untuk menyerang Hillary dibuat sedemikin kontras seperti menganalogikan politikus itu dengan kecoak yang harus dibasmi. Sehingga cara untuk memenangkan Trump tak lain adalah dengan membenci Hillary.
Secara akademis, metode itu sebagian besar diambil dari karya Michael Kosinki dari Psychometrics Center of Cambridge University, di mana ia bersama rekan-rekannya mengembangkan suatu sistem pembuatan profil personal berdasarkan data daring secara umum, Facebook-likes, dan data dari ponsel pintar.
Pada akhirnya, semua perjalanan Cambridge Analytica mesti usai setelah mencuatnya senarai laporan investigasi dari The Guardian dan Channel 4 News tersebut. Sumber terakhir menjadi bukti otentik karena media tersebut berhasil merekam secara diam-diam obrolan pemimpin firma itu, Nix, dengan salah satu calon kliennya untuk memenangkan pemilu di Sri Lanka. Alexander Nix berkata bahwa ia menggunakan suap, prostitusi, dan riset yang berseberangan untuk membuat lawan kliennya jatuh.
Menjalar ke Seluruh Dunia
Apa yang telah terjadi di Amerika Serikat dan Inggris adalah segelintir dampak politis yang terjadi berkat pemanfaatan data. Dalam lanskap yang lebih mendunia, SCL Group juga dianggap telah berperan dalam beberapa peristiwa politik di berbagai negara sejak awal kemunculannya, yang bahkan dilakukan sebelum era internet atau Facebook. Setidaknya dalam investigasi Channel 4 menunjukkan ada sekitar 200 klien yang pernah mendapatkan pelayanan dari induk grup, SCL, dan Cambridge Analytica.
Secara periodik, Afrika Selatan (1994) menjadi salah satu sorotan pertama saat berakhirnya politik Apartheid dan menjadikan semua golongan bisa berpartisipasi dalam pemilu. Dalam lansiran Voa News, terdapat sebuah partai politik—yang kemungkinan besar pro Nelson Mandela—mempekerjakan SCL untuk mengurangi kekerasan selama pemilu masa itu.
Di Asia Tenggara, yakni Thailand (1997) dan Indonesia (1998), SCL merangsek saat terjadi krisis ekonomi besar-besaran. Mengutip Quartz, di Indonesia, SCL dipinang pihak prodemokrasi dan berhasil membentuk opini massa kaum muda untuk menggulingkan Soeharto. Adapun setelahnya, SCL, atas permintaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kembali berupaya mencukupkan masa kepemimpinan B.J. Habibie untuk kemudian memenangkan Gus Dur pada pemilu 1999. SCL berhasil membentuk branding baik terhadap Gus Dur.
Mengacu tayangan The Great Hack, beberapa negara seperti Ukraina (2004), Trinidad-Tobago (2009), India (2010), Kolombia (2011), Italia (2012), Kenya (2013), Antigua (2013), Malaysia (2013), Argentina (2015), dan beberapa negara lain juga disebut meminta layanan spesial dari Cambridge Analytica. Sebagian besar selalu mengacu pada perebutan kekuasaan.
Di Trinidad-Tobago, misalnya, saat Kamla Persad-Bissessar berupaya meraih kekuasaan sebagai perdana menteri, hanya terdapat dua partai besar, yakni partai yang mewakili ras kulit hitam dan Indians. Cambridge Analytica bekerja untuk memenangkan Indians. Mereka menggagas kampanye bertajuk “Do so!” dengan simbol tangan menyilang yang menandakan penolakan terhadap pemerintahan sebelumnya. Mereka menginisiasi para pemilih muda lokal untuk bersikap apatis dan melakukan golput. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Indians untuk mengungguli selisih suara.
Kasus lain juga diketahui muncul di Myanmar. Seperti dilansir The Guardian soal bagaimana berita bohong di Facebook berhasil membentuk opini publik untuk membenci etnis Rohingya hingga bermuara pada genosida. Hingga Agustus 2018, terhitung 25.000 orang terbunuh dan 700.000 orang pergi meninggalkan Myanmar.
Beberapa persoalan lain juga muncul seperti Intelejen Rusia yang menyebarkan gagasan “Black Lives Matter” yang merepresentasikan kulit hitam dan membenturkannya dengan “Blue Lives Matter” yang merepresentasikan kulit putih di Amerika Serikat. Menurut paparan Cadwalladr, keduanya sama-sama diinisiasi Rusia untuk melakukan adu-domba. “Agar negara melawan dirinya sendiri,” tukasnya.
Hingga hari ini polemik mengenai isu pemanfaatan data personal belumlah usai. Itu menyusul pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan kembali berlangsung pada 2020 mendatang. The Guardian bahkan merilis halaman khusus dan menyajikan secara periodik isu mengenai Cambridge Analytica yang dianggap akan berevolusi menjadi bentuk lain. Disusul beberapa media seperti APNews yang sudah menulis perihal orang di balik layar kampanye Trump 2020 yang tak lain adalah mantan staf dari Cambridge Analytica sendiri.