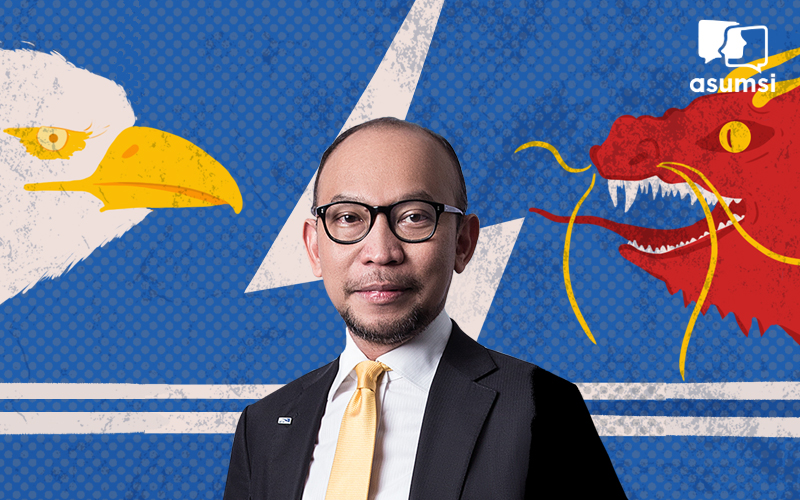Chatib Basri: Regulasi Ketenagakerjaan Menghambat Daya Saing Sektor Industri
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina menjadi fase baru dalam dinamika perdagangan internasional. Meski terkesan suram, sebenarnya ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Chatib Basri, dalam episode terbaru “Asumsi Bersuara with Rayestu.”
Salah satu implikasi besar dari perang dagang adalah penerapan tarif terhadap barang-barang produksi Cina. Chatib menilai bahwa hal ini akan membuat para pengusaha memindahkan pabrik-pabrik mereka ke negara lain. Bangladesh dan Vietnam, misalnya, sudah mulai merasakan akibat perubahan ini.
Bangladesh membuka diri untuk pabrik-pabrik tekstil baru, sedangkan perusahaan-perusahaan elektronik seperti Samsung mulai membuka pabriknya di Vietnam. Jika bisa menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar, sangat mungkin Indonesia merebut keuntungan dari tren ini.
“Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah kenapa nggak Indonesia?” kata Chatib.
Umumnya, keputusan perusahaan memindahkan pabriknya ke suatu negara berangkat dari empat faktor. Keempat faktor tersebut adalah perkembangan teknologi, sumber daya alam, kondisi pasar, dan kondisi ketenagakerjaan di negara yang dituju. Tentang poin yang pertama, Chatib berkata, “Kalau dia mau teknologi, mungkin dia lebih baik pergi ke Thailand atau Penang, atau Singapura, karena kapasitas human capital kita masih terbatas.”
Kondisi ini menyisakan tiga faktor lain. Tentang faktor kedua, SDA, Indonesia dianggap berkecukupan. Namun, Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada ketersediaan SDA.
Dari sisi faktor ketiga, pasar domestik, Indonesia juga dapat bersaing karena merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Kendati demikian, jika orientasinya pasar domestik, seorang pengusaha kehilangan potensi ekspor yang awalnya merupakan tujuan utamanya berinvestasi di Indonesia.
Indonesia Harus Lebih Kompetitif
Tersisa satu faktor, yakni kondisi ketenagakerjaan. Jika suatu perusahaan multinasional masuk ke Indonesia dengan dorongan faktor ketenagakerjaan, artinya ia bermaksud membangun bisnis yang bersifat padat karya.
“Jadi satu-satunya yang bisa kita manfaatkan di sini itu adalah tenaga kerja, kalau dia (pengusaha) masuk ke tenaga kerja, tentu dia akan masuk ke sektor yang namanya padat karya. Kalau saya mau sektor saya padat karya, tentu saya harus hire, saya harus serap tenaga kerja, nah kalau bisnis, itu kan nggak ada jaminan bisnis saya untung terus,” ucap Chatib.
Dari faktor ketenagakerjaan, Chatib menilai Indonesia perlu mengkaji ulang regulasi. Aturan-aturan yang kini berlaku, katanya, membuat Indonesia menjadi kurang menggiurkan di mata pengusaha.
“Dalam bisnis kadang untung, kadang rugi. Kalau saya lagi rugi, jumlah pekerja bisa saya turunkan. Tapi kalau ketika mau memecat pegawai, saya harus bayar gajinya 95 minggu, saya nggak sanggup. Sementara di Vietnam itu cuma 60 minggu, jadi orang akan bilang, ‘Wah, saya kalau masuk Indonesia, saya nggak mau, apalagi dari awal saya udah harus cadangkan uangnya’,” ungkap Chatib.
Permasalahan lain yang ditemukan adalah ketidakmampuan regulasi ketenagakerjaan melindungi pekerja seperti semestinya. Pengusaha yang memutuskan untuk membuka pabrik di Indonesia memilih untuk mengelabui peraturan dengan mekanisme tenaga kerja kontrak. Bukannya melindungi, hal ini justru semakin merugikan pekerja.
“Justru dengan ini tenaga kerja kita tidak terlindungi, karena tidak jadi tenaga kerja tetap. Jadi peraturan tenaga kerja ini seperti hire tax (pajak penyerapan tenaga kerja). Investor menghindari ini. Itu yang menjelaskan kenapa share dari sektor padat karya manufaktur per PDB itu terus turun di dalam lima belas tahun terakhir. Karena orang menghindari sektor itu, dia masuk ke sektor padat modal, dia masuk ke sektor sumber daya alam, itu yang menjelaskan kenapa investasi kita di SDA naik terus,” ucap Chatib.
Meski Berkurang, Kontribusi Sektor Industri Masih Besar
Berbicara mengenai turunnya kontribusi manufaktur ke PDB, perlu analisis yang lebih luas. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, penurunan kontribusi manufaktur ke PDB merupakan hal yang wajar. Bahkan secara global, sudah tidak ada lagi negara dengan kontribusi manufaktur mencapai 30% seperti Indonesia pada tahun 2001.
“Meski waktu itu kontribusi industri hampir 30% dan kita hampir take off, tetapi berhenti karena krisis ekonomi yang dipicu oleh keuangan,” ujar Menteri Airlangga dalam sebuah keterangan resmi di bulan Desember 2018 yang lalu, seperti dilansir dari Bisnis.com.
Situasi 2001 dan 2018 tentu berbeda. Pada 2017, Bank Dunia menerbitkan data: rata-rata kontribusi manufaktur negara-negara industri hanya sebesar 17%. Lima negara yang mencatatkan kontribusi lebih besar dari rata-rata tersebut adalah Cina (28,8%), Korea Selatan (27%), Jepang (21%), Jerman (20,6%), dan Indonesia (20,5%).
Kontribusi sektor industri bagi PDB Indonesia pada 2018 juga tidak jauh berbeda. Sektor ini berkontribusi sebesar 19,82%. Kontribusi ini juga masih menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya seperti perdagangan (13%) atau pertambangan (8,03%). Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri Indonesia masih bersaing dan menyumbang secara signifikan.