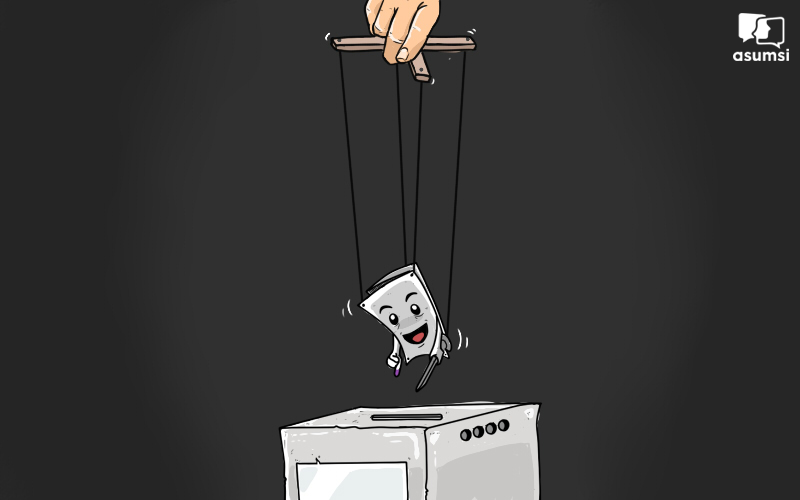Partisipasi Politik Semu
Pemilu 2019 menjadi panggung yang paling gampang untuk menyadari berbagai karakter pemilih. Ada tipikal pemilih yang loyal terhadap partai atau tokoh, ada juga yang mengutamakan program sang calon pemimpin. Partisipasi politik di tanah air dalam pesta demokrasi kali ini diklaim meningkat dari perhelatan sebelumnya.
Soal karakter pemilih, di Jakarta, misalnya, kita masih mendengar obrolan sehari-hari warganya yang memilih calon pemimpin berdasarkan berbagai faktor. Ada yang mempertimbangkan kinerja dan pencapaian, faktor fisik, bahkan usia.
“Gue suka dan bakal pilih Sandiaga Uno karena ganteng dan masih muda, idaman banget pokoknya.”
“Gue sih tetep pilih Pakde Jokowi karena udah terbukti kinerjanya selama menjabat di periode pertama kemarin.”
“Gue pilih Prabowo karena tegas, punya ideologi kuat, dan pidatonya berapi-api.”
“Gue pilih Ma’ruf Amin karena negara kita bakal kuat secara agama.”
Dalam spektrum yang lebih luas, Firmanzah menjelaskan lebih rinci dalam bukunya Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas (2012: 113), bahwa berbagai tipikal pemilih itu bisa dipahami lebih dulu lewat dua poin penting; pemilih yang berorientasi policy-problem-solving (disebut juga orientasi kebijakan) dan berorientasi ideologi.
Baca Juga: Refleksi Pemilu 2019: Pemilu Untuk Siapa?
Pemilih yang beorientasi kebijakan, dalam sikapnya akan menggunakan rekam jejak dan sederet pencapaian kerja untuk menilai si calon pemimpin pilihannya. Sementara pemilih yang berorientasi ideologi, jelas akan mempertimbangkan soal sejalannya pemikiran dengan calon pemimpin yang dipilih.
Tipikal-tipikal Pemilih dalam Kontesasi Politik
Lebih rinci lagi, setidaknya ada empat karakter untuk memahami perilaku pemilih. Karakter pertama adalah pemilih rasional, yang menggunakan rekam jejak dan program kerja si calon pemimpin. Tipikal pemilih ini bakal memperhitungkan matang-matang setiap program kerja si calon pemimpin, apakah nantinya bisa dicapai atau tidak.
Pemilih ini sebetulnya tak terlalu mementingkan faktor ideologi suatu partai dari si calon pemimpin. Meski tak dipungkiri pula bahwa tipikal pemilih ini, dalam hal tertentu terkadang juga tetap mempertimbangkan faktor ideologi dalam menentukan pilihannya.
Karakter kedua adalah pemilih kritis, yang dalam pilihan politiknya mempertimbangkan dua hal sekaligus yakni atas dasar kebijakan dan atas dasar ideologi. Jadi tipikal pemilih ini lengkap lantaran si calon pemimpin akan dilihat dari sisi personal dan rekam jejak, sisi program kerja yang ditawarkan, dan juga citra partai politik yang melekat padanya.
Peneliti Politik Cakra Wikara Indonesia Dirga Ardiansa menjelaskan bahwa bagi warga, yang terpenting kandidat itu bukan hanya soal figur semata, tapi politik itu juga mendorong agar kebutuhan masyarakat secara kolektif itu bisa terpenuhi. “Sehingga dalam politik, pemilih itu bukan hanya soal memilih pemimpin saja, tapi juga sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang dibutuhkan masyarakat,” kata Dirga saat berbincang dengan Asumsi.co di Jakarta, Jumat (30/08/19).
Misalnya saja masyarakat butuh akses transportasi yang cepat, layanan kesehatan yang berkualitas, fasilitas pendidikan yang baik. Sehingga semua kebutuhan masyarakat itu memang harus ada di dalam visi dan misi si kandidat sehingga nanti bisa diwujudkan sesuai yang diharapkan masyarakat.
Menurut Dirga, visi dan misi yang terbuka dari si calon pemimpin tentunya bakal mendorong supaya masyarakat sama seperti di beberapa negara maju. “Masyarakat itu penting banget posisinya. Masyarakat itu harus melihat kembali kepentingan mendasarnya seperti apa, supaya nggak kecewa di belakang.”
Banyaknya faktor yang jadi pertimbangan membuat pemilih kritis akan melakukan banyak analisa terhadap si calon pemimpin. Menariknya, jika si pemilih sama sekali tak mendapatkan kriteria yang dimaksud dalam proses analisa tersebut, maka ia bisa saja akan golput.
Karakter ketiga adalah pemilih skeptis, yang sama sekali tak peduli dengan latar belakang ideologi apapun dari si pemilih. Tipikal pemilih ini juga tak yakin dengan program kerja yang ditawarkan oleh si calon pemimpin dan menilai hal itu tak akan berdampak langsung ke masyarakat.
Baca Juga: Pembunuh Demokrasi dan Perang dalam Pemilu 2019
Sementara karakter keempat adalah pemilih tradisional, yang dianggap paling mudah dimobilisasi terutama pada masa kampanye. Orang-orang yang masuk dalam karakter pemilih tradisional memang cenderung loyal dan menganggap apa saja yang disampaikan si calon pemimpin yang dipilihnya, itu selalu benar.
Pada musim Pemilu 2019, tipikal pemilih tradisional ini mudah sekali ditemukan. Di ruang-ruang media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, pemilih ini tak takut untuk selalu menabuh genderang perang, berdebat, mempertahankan ide dan gagasan si calon pemimpinnya. Klaim kebenaran selalu jadi tumpuan, hoaks pun bukan tak mungkin disebarkan, sehingga pada akhirnya pemilih ini dinilai cukup berbahaya dalam iklim demokrasi.
Partisipasi Politik Tinggi tapi Semu
KPU mengklaim partisipasi pemilih di Pemilu 2019 mencapai 81%, meningkat dari Pilpres 2014 yang hanya mencapai 70% dan Pileg 2014 pada angka 75%.
Namun, partisipasi pemilih dalam perhitungan pemerintah tentu hanya sekedar keikutsertaan masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya saja, bukan partisipasi-pastisipasi lain. Padahal, jika ingin ditarik lagi, partisipasi politik pemilih itu harusnya lebih dari sekedar mencoblos saja.
Gabriel Almond (1999) menjelaskan bahwa partisipasi politik itu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan di mana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer. Peran mereka sebagai aggregator politik (penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya.
Menurut Almond, setidaknya ada tiga kategori partisipasi politik yakni interest articulation (artikulasi kepentingan), interest aggregation (penyatuan kepentingan), dan interest articulation (artikulasi kepentingan).
Sementara itu, ada dua jenis pola partisipasi politik menurut Almond, yakni pola konvensional, yang ditandai dengan bentuk-bentuk partisipasi yang umum dan lazim ditemui. Misalnya partisipasi dalam hal pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan, bergabung dengan partai politik, berkomunikasi secara individual dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif.
Sementara pola non-konvensional yakni bentuk-bentuk partisipasi yang tidak umum dan tidak lazim ditemui. Misalnya saja lewat pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan, perang gerilya, makar, hingga revolusi.
Partisipasi politik masyarakat selama ini kerap kali tak mempedulikan hal-hal substansial semacam program kerja dari sang kandidat. Padahal, sejalan dengan Almond, partisipasi politik itu sifatnya luas. Maka dari itu, cakupan program kerja, apalagi visi-misi seorang kandidat pemimpin, punya posisi paling krusial dan menentukan jika nanti terpilih sebagai pemimpin sehingga perlu diperhatikan.
Sayangnya, baik si calon pemimpin hingga para pemilih, sebagian besar masih kurang paham terhadap poin visi-misi dan program kerja yang ditawarkan. Ada calon-calon pemimpin yang misalnya tak paham dengan visi-misinya sendiri, sehingga untuk menjelaskannya saja begitu sulit. Situasi itu semakin diperparah dengan sikap masyarakat yang juga tak mau peduli dengan hal itu.
“Dokumen visi-misi mungkin nggak dipahami sama si calon pemimpin karena nggak dibuat oleh si kandidat itu sendiri. Bisa saja visi-misinya itu dibuat oleh banyak tangan seperti partai politiknya, oleh tim sukses, atau oleh tekanan kelompok di sekitarnya yang punya kepentingan,” ucap Dirga.
Padahal, penting bagi si calon pemimpin untuk membuka secara rinci visi-misi dan program kerjanya, apalagi visi-misi itu bersifat abstrak, sehingga harus dibeberkan lebih rinci menjadi program kerja yang bisa diwujudkan. Sebab, program kerja itulah yang paling enak dikunyah dan dicerna masyarakat.
Visi-misi si calon pemimpin juga harusnya tak sedekar jadi pemanis visual di baliho-baliho, tapi mestinya draft visi-misi tersebut bisa dibawa ke meja untuk didiskusikan, dikoreksi, dirancang bersama masyarakat. Untuk apa? Agar kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat bisa terakomodir dengan baik, dan menghindari masuknya kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Misalnya kalau kurang sreg dengan poin visi-misinya, harusnya bisa dirombak agar sesuai dengan tuntutan perubahan dan tentunya tuntutan masyarakat. Dari perspektif kandidat, harusnya visi-misi itu bisa dirumuskan dengan melibatkan warga, kelompok masyarakat, sehingga banyak masukan yang mengakomodir kepentingan bersama.
“Kalau visi-misi dan program kerja itu nggak dibahas bersama, ya pada akhirnya masyarakat hanya akan dapat pride dan kemenangan saja dari si kandidat yang dipilih, bukan kebutuhan yang semestinya.”
Partisipasi tinggi namun semu inilah yang ditakutkan berpotensi muncul di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mendatang. Apalagi, masyarakat Indonesia saat ini cenderung terfragmentasi menjadi individu-individu saja. Dalam konteks ini, perlu ada peran aktif kelompok-kelompok tertentu untuk melibatkan masyarakat dalam penggodokan visi-misi serta program si calon pemimpin.
“Jadi kalau basisnya individu-individu yang lepas, itu kebutuhan kepentingannya tidak bisa diagregasi, begitu terserak dan sulit dikompilasi. Jadi perlu ada perantara atau gerakan kelompok sosial, yang bisa mengorganisir karena punya peran untuk mengagregasi kebutuhan-kebutuhan yang paling strategis bagi masyarakat sehingga itu yang disuarakan dan terus dikawal,” kata Dirga.