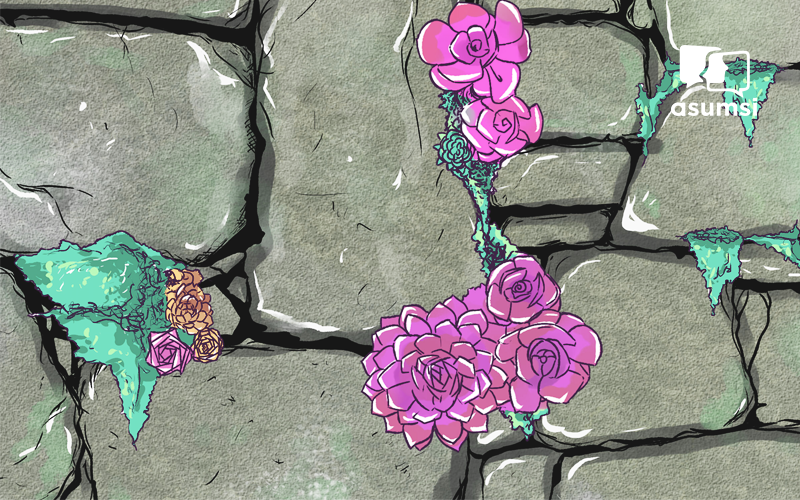Lahir seorang Rich Brian, Tenggelam Beratus Ribu
Rich Brian menyebut “Kids” lagu istimewa saat mengumumkan peluncurannya lewat Twitter. Tak bisa lain, memang. Musiknya sedap, boom bap dengan cita rasa kiwari, dan sang MC bukan lagi badut dalam “Dat $tick” atau pecundang dalam “History.”
Kali ini Brian berbicara tentang diri yang gagah sekaligus rawan, yang siap menaklukkan dunia tetapi penuh hormat terhadap segala yang menaunginya: keluarga, kultur hip hop, Indonesia, Asia, dan tradisi diaspora. Kedalaman membuat lagu ini terasa tulus, dan ketulusan itu menggugah.
“Fuck bein’ one of the greatest, I’m tryna be the greatest one,” ujarnya. Dan pada baris lain, dia mengatakan: “Everyone can make it, don’t matter where you’re from.”
Sebagaimana Presiden Jokowi yang tersenyum kebapakan saat lagu itu diputarkan untuknya di istana, saya tentu berharap cita-cita Brian terwujud. Saya juga senang membayangkan bahwa pencapaian demi pencapaiannya menyalakan api dalam diri orang-orang lain. Namun, pada saat yang sama, hasrat Brian yang meluap-luap terhadap kesuksesan dalam “Kids” mengingatkan saya kepada sebuah perkara sedih.
“Umur kita hampir 30 tahun, dan aku belum jadi apa-apa,” kata seorang teman baik saya suatu kali. “Such a failure.”
“Memangnya situ mau jadi apa, Bung?” tanya saya.
“Setidaknya di umur 30 sudah bikin album musik atau apalah,” katanya.
Pengantar daftar tahunan “30 Under 30” Forbes pada 2014 menyatakan bahwa anak-anak muda masa kini beruntung, sebab dunia digital yang dinamis memungkinkan kita untuk langsung menguber tujuan-tujuan besar tanpa berlama-lama mematangkan diri seperti angkatan terdahulu. Namun, yang tak dikatakan catatan tersebut, kesempatan menggapai cita-cita yang terbuka lebar hadir bersama tuntutan semena-mena: sukses dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Usia 30, seperti yang dikhawatirkan teman saya, memang telah jadi semacam simpang di mana orang-orang sukses dan gagal berpisah. Menurut Paul Graham, seorang venture capitalist ternama, para pendiri perusahaan yang berusia di atas 32 tahun cenderung lebih sulit mendapatkan pendanaan.
Kita, ujar Chairil Anwar dalam puisinya “Catetan Th. 1946,” bagai anjing diburu. Dan hari-hari ini, lebih dari 70 tahun kemudian, sama saja. Teman saya tentu bukan satu-satunya yang cemas mendapati bahwa hidupnya tak sesuai dengan naratif kesuksesan. Padahal, tak peduli seberapa erat kita memeluk keyakinan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama, kesuksesan, lebih-lebih di usia muda, menuntut bakat, akses, daya tahan, ambisi, dan mungkin hal-hal lain lagi. Tentu sedikit saja orang yang memiliki semuanya.
“Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu,” kata Chairil dalam puisi yang sama. “Keduanya harus dicatat, keduanya dapat tempat.” Jika si besar hari-hari ini adalah orang yang memenuhi tuntutan kesuksesan, katakanlah seperti Rich Brian, tempat macam apa yang patut diberikan kepada mereka yang tenggelam?
Saya berharap kita bisa lebih relaks. Orang yang belum jadi apa-apa saat berumur 30 tahun mungkin saja mekar di kemudian hari, seperti Paul Cézanne atau Mark Twain. Dan yang terpenting, saya kira, kita mesti bertanya: kenapa, sih, orang harus sukses?
“Masyarakat kita tak pernah puas menelan cerita-cerita tentang kekayaan dan kesuksesan,” kata Paul Dolan, Kepala Departemen Psychological and Behavioural Science di London School of Economics. “Tanpa keduanya, kita gelisah dan menderita.”
Naratif-naratif sosial itu memandu hidup kita, menyediakan jalan. Namun, ujung-ujungnya, “lebih dari ingin memastikan diri selalu berada di jalan itu, kita bahkan memarahi orang-orang yang melenceng,” kata Dolan. Di titik inilah pikiran kita terperangkap: hanya ada satu cara menjalani hidup.
Hanya dengan berpikir demikian kita menganggap yang tak sukses, yang tak menjadi apa-apa, sebagai kesia-siaan.
Kita terbiasa mengira akan semakin bahagia bila semakin banyak harta dan kesuksesan bertumpuk, bila terus-terusan meraih lebih. Padahal, sebagaimana ditunjukkan riset American Time Use Survey (ATUS), orang-orang berpenghasilan di atas US$100 ribu tak lebih bahagia ketimbang yang mendapat kurang dari US$25 ribu. Bahkan, orang-orang dari kelompok berpenghasilan paling tinggi justru paling sering mengaku merasa hidupnya hampa.
Menurut Penelitian City & Guilds pada 2012, 87% floris dan tukang kebun di Inggris merasa bahagia. Jumlah itu jauh lebih tinggi ketimbang bankir (44%) dan pengacara (64%), sekalipun kelompok profesi yang terakhir jelas lebih makmur.
Orang-orang yang berbahagia, saya kira, mengerti bahwa kesuksesan bukanlah harga mati.
Kalau ada kesempatan, saya ingin mengatakan kepada teman saya bahwa tak peduli sukses atau tidak, menjadi besar atau tidak, dia tetaplah salah satu orang paling menyenangkan yang saya kenal. Dan atas dasar itu saja, hidupnya patut dirayakan.
“Jauh di dasar jiwamu bertampuk suatu dunia,” kata Chairil dalam sebuah puisi untuk sahabatnya, penyair LK Bohang. Dan pada baris lain, ia memuji sepenuh hati, “Duka juga menengadah melihat gayamu melangkah.”
Tak ada satu pun karya Bohang yang saya ingat. Mungkin karena memang tak ada yang istimewa. Bagi saya, ia cuma satu dari ribuan nama yang tenggelam dalam sejarah sastra Indonesia, tetapi Chairil Anwar merayakannya.