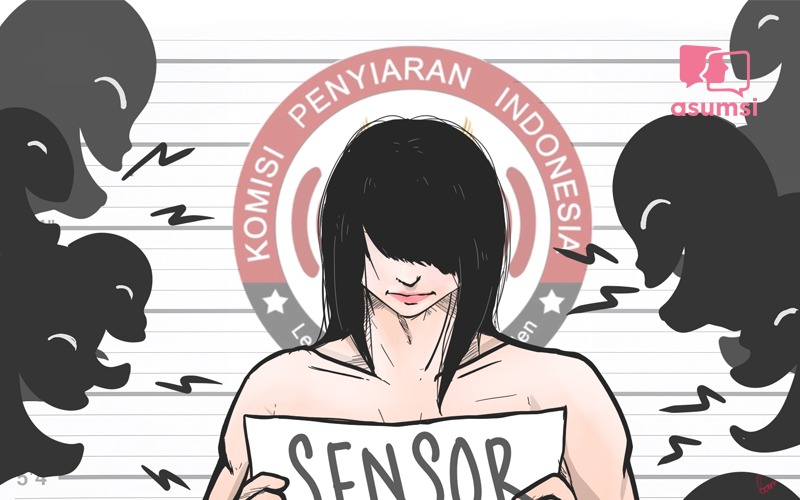Olok-olok Televisi kepada Kelompok Transgender
Film Pretty Boys (2019), yang dibintangi oleh Vincent Rompies dan Desta Mahendra, berintensi mengkritik budaya televisi. Film ini memperlihatkan bagaimana seseorang mesti mengorbankan jati dirinya demi bisa hadir di layar kaca. Namun, alih-alih bersikap kritis, Pretty Boys justru melanggengkan stigma tentang transgender—khususnya transpuan yang seringkali jadi bahan olok-olok di TV.
Dalam Pretty Boys, terdapat banyak karakter transpuan dan laki-laki kemayu. Anugrah (Vincent) dan Rahmat (Desta) juga mesti berpura-pura jadi perempuan ketika mengisi sebuah acara komedi di TV. Gestur dan perilaku mereka mengundang tawa para penonton.
Film ini mengutarakan perkataan-perkataan yang transfobik, seperti mempertanyakan apakah gelagat kemayu tersebut dapat menular, menjadikan karakter kemayunya punya intensi jahat, hingga menganggap tindakan berpura-pura jadi transgender sama problematisnya dengan tentara yang ditugaskan di wilayah konflik dan menculik orang.
Aulia Adam dalam ulasannya di Tirto menganggap film ini tidak sensitif terhadap transgender. Sebagai kelompok yang terpinggirkan, transgender sering mengalami diskriminasi di kehidupan nyata. Alih-alih memberi transgender kesempatan berbicara balik terhadap penindasan, kelakar-kelakar dan perilaku kemayu yang dibingkai negatif dalam film ini justru memperkokoh stereotip.
Apa yang salah dari membingkai transpuan sebagai objek tertawaan? Bagaimana karakter transpuan dan laki-laki kemayu digambarkan dalam program-program televisi?
Stereotip Transgender dan Dampaknya
Di Indonesia, transpuan lebih dikenal dengan istilah waria (wanita pria). Karakter-karakter transpuan telah muncul di acara-acara televisi maupun di film Indonesia sejak lama. Detara Prastyphylia mencatat bahwa transpuan pertama kali dijadikan bahan tertawaan pada 1979, yaitu oleh pelawak Srimulat bernama panggung Tessy. Ia seringkali tampil menggunakan riasan dan pakaian seperti perempuan untuk melawak.
Sejak saat itu, muncullah komedian-komedian lain yang berlagak seperti perempuan dalam acara televisi, seperti Aming dalam Extravaganza, Aziz Gagap dalam Opera Van Java, hingga Olga Syahputra dalam berbagai program—seperti Dahsyat, Pesbukers, dan lain-lain.
Firman Imaduddin selaku peneliti Remotivi mengamini adanya stereotip tertentu yang melekat pada transgender di TV. “Sebagai kelompok minoritas, masyarakat tidak sering bersinggungan dengan mereka di kehidupan nyata. Kita berakhir mengenal mereka cuma lewat media dengan cara pandang yang terbatas,” ujar Firman.
“Mereka (transpuan dan pria kemayu) kemudian dianggap aneh, dipandang sebagai tontonan. Karakter mereka direduksi menjadi sekadar bahan hiburan,” kata Firman.
Tak hanya transgender, Firman juga mencontohkan bagaimana para penyandang dwarfisme seringkali diidentikkan dengan komedi. “Stereotip yang sering muncul tentang penyandang dwarfisme adalah sering melawak, ceria, dan bisa di-ceng-cengin. Akhirnya masyarakat jadi punya asumsi tertentu terhadap perilaku mereka,” jelas Firman.
Asumsi-asumsi tersebut membuat penyandang dwarfisme mengalami perilaku diskriminatif di dunia nyata. “Ada riset yang mewawancarai orang-orang penyandang dwarfisme. Kebetulan salah satu subjek yang diwawancarai punya kepribadian yang bertolak belakang dengan persepsi di media. Dia pendiam, sensitif, dan nggak suka diledek. Akhirnya dia dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya karena nggak memenuhi ekspektasi mereka akan seorang penyandang dwarfisme,” kata Firman melanjutkan.
Misrepresentasi atau penggambaran yang tidak utuh terhadap kelompok minoritas punya dampak serius. Penelitian bertajuk “Media Representation & Impact on the Lives of Black Men and Boys” oleh The Opportunity Agenda memperlihatkan dampak dari penggambaran negatif media massa terhadap orang kulit hitam.
Publik memperlakukan orang kulit hitam dengan penuh curiga, menyebabkan mereka punya usia harapan hidup yang rendah. Seorang remaja berkulit hitam bernama Michael Brown, misalnya, ditembak sebanyak 12 kali oleh seorang polisi karena ia dianggap berbahaya. Padahal, si remaja tidak melakukan perlawanan dan telah mengangkat tangan.
Stereotip ini juga membuat mereka sulit untuk mengisi peranan di luar persepsi yang telah melekat di publik. “Kondisi marjinal membuat mereka hanya diterima ketika mengisi peranan tertentu di masyarakat. Transpuan, misalnya, punya opsi pekerjaan yang semakin terbatas. Peluang pekerjaan mereka terpojok ke menjadi pekerja seks komersial, penata rambut di salon, atau mengisi stereotip komedi di showbiz,” kata Firman.
Merlyn Sofjan, seorang transpuan yang pernah menjadi Putri Waria 2006, juga menekankan pentingnya representasi. “Memang, waria nggak semuanya baik. Yang negatif juga ada. Tapi aku ingin mengingatkan bahwa jangan melihat manusia dari kelaminnya. Kita manusia ini unik dan beragam. Representasi itu menolong teman-teman transgender untuk bisa dilihat secara utuh. Tidak digeneralisir sebagai satu hal, begitu,” kata Merlyn.
Kemunduran KPI
Pada 2016, representasi kelompok transpuan kembali dicederai TV. Surat edaran KPI dengan nomor 203/K/KPI/02/2016 melarang TV menampilkan “pria berpenampilan kewanitaan”. Pada Juli 2019, tayangan “Brownis” diancam oleh KPI untuk dihentikan karena menampilkan seorang bintang tamu laki-laki yang berdandan dan berpakaian seperti perempuan.
Menurut Firman, surat edaran ini sebenarnya menyalahi buku panduan KPI sendiri, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pasal 15 mewajibkan lembaga penyiaran untuk melindungi hak dan kepentingan kelompok marjinal, seperti orang yang punya orientasi seks dan identitas gender tertentu, orang yang memiliki cacat fisik dan/atau mental, orang yang mengidap penyakit tertentu, dan orang dengan masalah kejiwaan.
Lembaga penyiaran juga dilarang untuk menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang-orang dari kelompok tersebut.
“Dalam P3SPS ada larangan untuk mendiskriminasi orang karena identitas gendernya, apalagi mengancam menghilangkan lapangan kerja orang tersebut. Remotivi pernah membuat surat pernyataan untuk menghapus surat edaran [KPI]. Sebab, kekuatan ikatannya pun lemah, jauh di bawah buku panduan. Seandainya ada pertentangan, surat tersebut seharusnya jadi tidak relevan,” kata Firman.
Merlyn Sofjan juga mengatakan bahwa terdapat kemunduran cara berpikir komisioner KPI. Katanya, ketika Ade Armando menjabat sebagai anggota KPI periode 2004-2007, transgender tidak dilarang untuk tampil di TV. “Yang dilarang adalah ketika seorang laki-laki cis-gender bepura-pura jadi waria dan menjadi bahan lawakan. Tapi kalau waria itu sendiri hadir untuk bercerita tentang hidup dan komunitas mereka, nggak masalah,” kata Merlyn.
Ade Armando pernah mengungkapkan rasa pesimistiknya terhadap kinerja anggota KPI periode 2016-2019. Dilansir oleh Tempo.co, Ade mengatakan bahwa kualitas mereka jauh dari kompetensi, integritas, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi anggota komisi penyiaran. Sementara, menurutnya, orang-orang yang punya pemahaman dan rekam jejak positif justru tidak lolos pemilihan oleh DPR.
Menurut Merlyn, mengucilkan waria dari dunia televisi berarti mengabaikan eksistensi transgender di Indonesia. “Padahal di dunia ini nggak hanya ada perempuan dan laki-laki. Kalau kita merujuk pada gender, ada gender sebagai konstruksi sosial. Bahkan dulu Pak Ali Sadikin, mantan gubernur DKI Jakarta (1966-1977), pernah membuat sebuah tempat khusus untuk pertunjukan waria. Sementara, sekarang ini sudah tahun berapa?” kata Merlyn.
KPI juga pernah berdalih melakukan pelarangan atas program yang menayangkan seorang laki-laki berbusana perempuan karena melanggar Pasal 15 ayat (2) P3SPS tentang larangan mengolok-olok seseorang dengan gender tertentu. Padahal, awalnya, alasan KPI melarang adalah karena, “program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak,” dan “program siaran dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku tidak pantas.”
“Pernyataan awal itu dihapus dari Instagram KPI, dan di-republish dengan mengganti argumen bahwa siaran televisi tersebut telah menjadikan kelompok transgender bahan lelucon. Itu memang bisa-bisanya mereka ngeles. Padahal jelas motivasi awalnya adalah pembatasan, bukan perlindungan,” kata Firman.
Namun, Merlyn tak memusingkan peraturan KPI yang membatasi kehadiran orang transgender di TV. “Orang sudah mulai meninggalkan TV dan beralih ke gadget. Jadi sebetulnya it’s okay-lah waria nggak boleh tampil di TV. Banyak panggung lain yang bisa diisi. Aku sendiri exist di Instagram dan Facebook,” kata Merlyn.