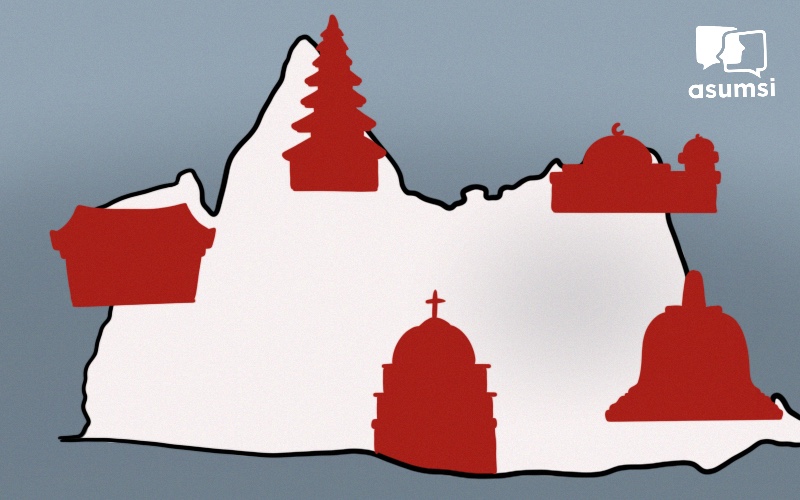Intoleransi Marak di Yogyakarta, Langkah Apa yang Harus Dilakukan?
Nama pelukis asal Semarang, Slamet Juniarto, sempat ramai jadi perbincangan di dunia maya dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, ia menjadi korban perlakuan diskriminatif dari warga yang membuat peraturan melarang non-muslim tinggal di Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Peristiwa ini pun menjadi sorotan dan sempat membuat Yogyakarta dianggap sebagai kota intoleransi.
Setelah kejadian itu ramai jadi sorotan, Slamet akhirnya diperbolehkan tinggal di perkampungan tersebut. Sementara itu, Bupati Bantul Suharsono akhirnya mencabut aturan yang melarang nonmuslim tinggal di Dusun Karet, Pleret, Bantul. Regulasi desa tersebut dinilai tak sesuai dengan aturan hukum yang ada di tingkat yang lebih tinggi.
“Aturan yang kemarin itu sudah enggak dipakai. Karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Suharsono di kantornya, Jumat, 5 April 2019.
Aturan yang dimaksud ialah peraturan desa di Padukuhan Karet bernomor 03/Pokgiat/Krt/Plt/X/2015. Aturan itu disahkan pada 19 Oktober 2015 dengan ditandatangani oleh Ketua Dusun Karet, Iswanto, dan Ketua Pokgiat Ahmad Sudarmi. Isinya bahwa pendatang di Padukuhan Karet haruslah muslim. Warga keberatan jika ada warga non-muslim yang menetap sebagai pendatang baru.
Aturan Diskriminatif Itu Sudah Ada Sejak 2015
Di sisi lain, Pemerintah DIY sangat menyesalkan munculnya aturan diskriminatif di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul Yogyakarta. Kembali pada tahun 2015, aturan diskriminatif itu melarang warga non-muslim dan aliran kepercayaan lainnya unyuk tinggal di kampungnya meski hanya sebatas mengontrak.
“Gara-gara nila setitik itu, Yogya langsung dicap intoleran oleh masyarakat luas, kami menyesalkan sekali aturan seperti itu bisa muncul,” kata Sekretaris DIY Gatot Saptadi dalam konferensi pers, Jumat, 5 April 2019.
Dari kejadian di Dusun Karet itu, Gatot menuturkan pemerintah DIY kini mulai getol menelusuri aturan-aturan diskriminatif lain sejenis jikalau juga ada di wilayah lain. “Aturan seperti ini (diskriminasi agama) jelas ilegal, ini jelas salah, kami akan telusuri ada tidak aturan sejenis ini di tempat lain,” ucapnya.
Gatot menuturkan, Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X tak mau peristiwa Dusun Karet Bantul itu terulang. Ia mengatakan bahwa Sultan langsung membuat instruksi gubernur nomor 1/instr/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial yang mulai diberlakukan Kamis, 4 April 2019 yang ditujukan kepada para bupati dan walikota se-DIY.
Tiga Faktor Penyebab Utama Intoleransi di Yogyakarta Sejak 2012
Direktur Riset Setara Institute, Halili mengatakan bahwa terjadi peningkatan tindak intoleransi dan pelanggaran hak berdasarkan agama selama setidaknya enam tahun terakhir atau sejak tahun 2012 silam. “Jadi dalam isu SARA, kami melihat paling tidak sejak 2012 itu sudah ada peningkatan pelanggaran hak beragama terutama di Yogyakarta,” kata Halili saat dihubungi Asumsi.co, Senin 8 April 2019.
Menurut Halili, dari sisi kuantitas, jumlah tersebut cenderung naik turun, ada fluktuasi. Namun, sejak 2012, memang ada kecenderungan meningkat, meskipun jumlahnya naik turun, tapi trennya meningkat. “Paling tidak ada tiga faktor penyebab utama yang menurut kami determinan atau paling berpengaruh, berkontribusi, terhadap peningkatan ekspresi intoleransi di sini. Pertama, adalah soal kealpaan pemerintah lokal dan masyarakat untuk mengelola konservatisme keagamaan.”
Halili menjelaskan bahwa isu keagamaan dan konservatisme di Yogyakarta itu memang tidak pernah diurus, meski isu itu nyata adanya. Misalnya saja yang terjadi di sekolah-sekolah, di mana ada larangan atau tidak dibolehkannya siswa untuk hormat kepada bendera. Menurut Halili, hal itu jelas merupakan bentuk ekspresi intoleransi yang sangat mencolok bahkan cenderung radikal.
“Terhadap simbol-simbol saja mereka anti, apalagi terhadap nilai atau doktrin keagamaan yang berbeda. Jadi, ada kealpaan dalam mengelola intoleransi yang timbul akibat maraknya kelompok konservatif keagamaan.”
Sementara faktor kedua, terkait kapasitas aparatur negara di tingkat lokal yang kapasitasnya sangat rendah. Misalnya saja terkait kinerja intelijen daerah yang hampir tidak punya peran sama sekali untuk mencegah. Contohnya yang terjadi di pemakaman Bethesda, yang terjadi dua hari setelah instruksi Gubernur keluar.
Yang disayangkan, instruksi Gubernur itu tidak segera dibarengi dengan mobilisasi seluruh potensi atau resource yang dimiliki oleh daerah, termasuk intelijen. Tidak ada upaya untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa intoleransi yang kemungkinan muncul pasca keluarnya instruksi itu.
“Makanya kemarin itu yang menurut saya agak aneh adalah ketika misalnya kepolisian menjelaskan bahwa pembakaran salib di pemakaman Bethesda, itu dilakukan oleh gelandangan yang kedinginan dan ingin menghangatkan tubuhnya, itu jelas enggak masuk akal.”
Padahal, lanjut Halili, kalau memang ingin membuat api unggun, seharusnya tak perlu mengambil salib karena masih ada semak-semak, ada kayu-kayu kering, ada kertas-kertas yang bisa digunakan. “Kenapa harus mengambil kayu salib yang harus dicopot lebih dulu apalagi itu disemen kan? Itu tidak masuk akal.”
Kondisi itu lah yang semakin menegaskan bahwa mobilisasi aparat kepolisian di tingkat daerah itu tidak maksimal. Sementara faktor ketiga, adalah soal penegakan hukum. Jadi selama ini kasus-kasus yang pernah muncul sejak 2012 itu tidak diselesaikan dengan pendekatan hukum yang memberikan efek jera.
“Padahal kalau kita cek ke rumus dasarnya, bahwa setiap impunitas itu pasti akan memancing kegiatan lain yang lebih besar di masa yang akan datang. Impunitas itu ketiadaan penegakan hukum. Kalau hukum tidak ditegakkan, maka itu akan memberikan energi bagi para pelaku untuk mengulang atau pelaku lain untuk mengikutinya.”
Dua Pendekatan Efektif yang Bisa Dilakukan
Halili pun menegaskan bahwa jelas kinerja aparatur pemerintah memang masih lemah, apalagi sejak 2015 tak ada yang mendeteksi adanya aturan diskriminatif itu. Kalau bukan karena kasus Slamet, tentu perangkat daerah tak akan pernah tau dan mengerti bahwa ada aturan sediskriminatif di daerahnya.
“Ada persoalan kapasitas yang memang lemah. Ujungnya yang mau kita bilang adalah kita ini tidak memiliki semacam early warning system untuk memitigasi persoalan-persoalan intoleransi, mana yang intoleransi mana yang kearifan lokal. Mirisnya, kemarin itu sempat muncul bahwa peristiwa yang terjadi itu merupakan kearifan lokal di Dusun Karet, kan aneh.”
Halili pun mengatakan bahwa Setara Institute bersama rekan-rekan aktivis lainnya yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, sudah berupaya mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Menurut Halili, setidaknya ada dua pendekatan yang selalu mereka ajukan ke pemerintah.
“Kami sebagai NGO masyarakat sipil, selalu mendorong pemerintah untuk melakukan dua pendekatan. Pendekatan struktural, itu bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama membuat regulasi yang memungkinkan minoritas itu dijamin hak konstitusionalnya sebagai warga negara,” kata Halili.
Misalnya minoritas nasrani atau kristen di Gunung Kidul, untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama atas pendirian tempat ibadah. Maka kemudian pemerintah Gunung Kidul didorong untuk melakukan penguatan regulasi dengan menerbitkan SK Bupati tentang pendaftaran rumah ibadah, tempat ibadah yang ada di Gunung Kidul untuk dijamin sehingga tidak dipersekusi oleh mayoritas yang sering mempersoalkan perizinan
“Yang kedua, dengan pelibatan aktif institusi pemerintah yang ada. Kan kita punya Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kita dorong semua untuk terlibat aktif dalam upaya untuk membangun kerukunan dalam kemajemukan.”
“Nah sikap Bapak Bupati dan terakhir Gubernur terakhir yang mengeluarkan instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 itu bagian dari contoh nyata betapa instrumen institusi pemerintahan di tingkat lokal ini bisa mendukung pada dimensi struktur itu.”
Lalu, lanjut Halili, yang sifatnya bottom up, ada dimensi kultural, di mana pihaknya mendorong masyarakat sipil di Yogyakarta untuk mengambil langkah penting untuk saling menghormati. Misalnya pada kasus kerusakan Gereja Katolik St Lidwina Bedog, di Jalan Jambon Trihanggo No. 3, Gamping, Trihanggo, Sleman, DI Yogyakarta, masyarakat sipil bahu membahu langsung membersihkan puing-puing yang tersisa, lalu bagian media mensosialisasikan bahwa ada harapan toleransi pasca terjadinya intoleransi. Jadi ada pendekatan struktural dan ada pendekatan kultural, itulah yang kita perjuangkan.”