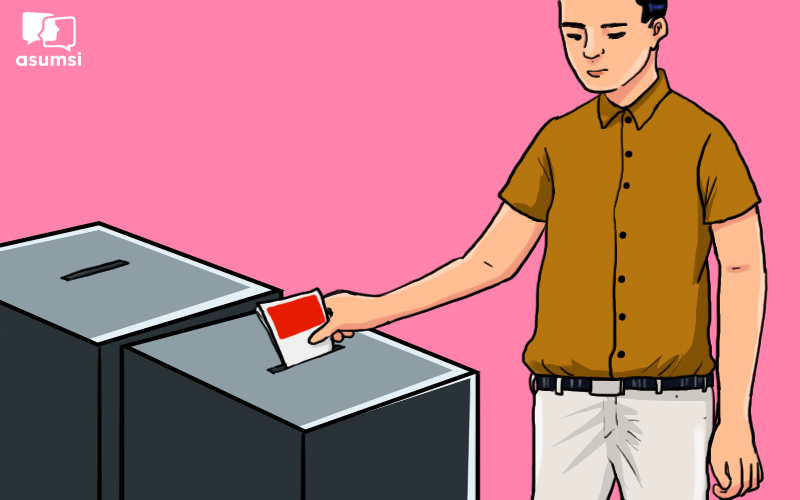Beda Pemilu dan Metode Kampanye Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi
Indonesia kembali akan menggelar hajatan besar bertajuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada 17 April nanti. Pesta demokrasi mendatang akan diselenggarakan untuk pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden dalam waktu bersamaan. Skema Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak (pileg dan pilpres), tentu sangat berbeda dengan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia pada era Orde Lama. Tak hanya itu saja, pemilu kali ini juga dipastikan berbeda dengan pemilu di era Orde Baru.
Terdapat perbedaan jelas dari beragam aspek pada gelaran pemilu yang terjadi di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Misalnya saja dari segi jumlah partai politik peserta pemilu, sampai metode kampanye. Rincian mengenai perbedaan gelaran pemilu dari ketiga periode tersebut diuraikan di bawah ini:
Kampanye Politik di Pemilu Pertama Era Orde Lama
Pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia terjadi di era Orde Lama tepatnya tahun 1955 atau 10 tahun pasca Indonesia merdeka. Pemilu 1955 merupakan satu-satunya pemilu yang terjadi pada masa itu. Pemilu tersebut dibagi menjadi dua tahap.
Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Lalu, tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Sementara itu, lima besar partai dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955 ini bukannya tanpa hambatan sama sekali. Bahkan butuh waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan segala perangkat-perangkat penyelenggaraan pemilu kala itu. Munculnya tekanan eksternal seperti serbuan kekuatan asing membuat rakyat Indonesia mau tak mau harus membagi waktu dan tenaganya untuk terlibat peperangan.
Meski kendala itu menghambat proses pemilu di Indonesia, tetap ada indikasi kuat pemerintah berkeinginan untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya saja dengan dibentuknya UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu. Dalam UU No. 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung), untuk menghindari distorsi akibat banyaknya warga negara yang buta huruf kala itu.
Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Pemilu 1955 yang diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan, berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Kala itu, Indonesia pun menuai pujian dari berbagai pihak termasuk negara-negara asing. Data yang dihimpun KPU mencatat bahwa kesadaran berkompetisi secara sehat pada Pemilu 1955 sangat tinggi. Meskipun calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
Urunan Dana Kampanye
Menariknya, metode kampanye yang terjadi di Pemilu 1955 sendiri sedikit banyak mirip dengan apa yang terjadi di era Reformasi. Hal itu terlihat dari budaya urunan dana kampanye yang ternyata sudah ada sejak Pemilu 1955 di era Orde Lama. Menurut Sejarawan Indonesia Anhar Gonggong, kala itu, bahkan rakyat juga ikut menyumbangkan uangnya secara sukarela untuk membantu dana kampanye dari partai yang didukung.
Anhar menyebut saat itu pengumpulan dana kampanye di Pemilu 1955 masih menggunakan karung atau kotak uang. Belum menggunakan rekening, seperti di era Reformasi. Rakyat yang datang pun memberikan sumbangan secara sukarela. Menurut Anhar, pengumpulan dana kampanye seperti itu merupakan langkah positif dalam pemilu karena secara tidak langsung akan mengajarkan calon pemilih untuk tidak menjual suaranya.
“Kalo rakyat datang ke suatu kampanye, itu mereka justru menyumbang. Jadi misalnya dalam ruangan ini atau di lapangan sana, maka di sudut-sudut tempat ini ada tempat uang atau bahkan karung biasanya,” kata Anhar Gonggong seperti dikutip dari Berita Satu TV, 1 Juni 2014. Lanjut Anhar, “Waktu itu, uang kita ada yang namanya ketip, ada sen, ada suku, ada tali, ada satu rupiah, ada satu ringgit, ada lima rupiah, dan seterusnya. Ada yang nyumbang satu sen dan itu yang paling rendah.”
Kampanye Politik di Era Orde Baru
Selama era Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama setelah absen penyelenggaraannya selama 16 tahun.
Pemilu pertama setelah Orde Baru ini diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Mereka yang terdaftar yakni Partai Katolik, PSII, NU, Parmusi, Golkar, Parkindo, Murba, PNI, Perti, dan IPKI. Lima besar pada pemilu itu adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Selama Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu.
Memasuki tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.
Monopoli Kampanye Golkar
Seperti dikutip dari hariansejarah.id, Rabu, 15 Agustus 2018, Golkar sebagai partai baru dalam politik Indonesia menjadi partai yang didukung oleh pemerintah dan ABRI. Dalam kampanye pertamanya, Golkar memilih tema “Politik no, Pembangunan yes” sebagai representasi keinginan pemerintah. Golkar juga sering kali mengungkit-ungkit kegagalan dan kelemahan partai politik di masa lalu dengan tujuan melumpuhkan partai politik ketika berkampanye.
Bahkan, kampanye Golkar juga diwarnai dengan paksaan. Seperti, sebagian besar pegawai negeri dan pamong desa dilarang berkampanye untuk partai pilihan mereka. Malahan, mereka diharuskan bergabung dan bekerja sama dengan Golkar dan memilih partai tersebut.
Golkar juga menyampaikan kampanye kepada masyarakat bahwa “menentang Golkar berarti menentang pemerintah” sehingga tidak akan ada pekerjaan atau pelayanan pemerintah bagi para penentang Golkar. Jabatan Ketua Golkar pun banyak diisi oleh para perwira militer yang bertugas mengawasi para pemimpin sipil dari dekat. Daftar para calon partai disaring dan banyak nama dikeluarkan dari daftar pemilihan. Lalu, pemimpin-pemimpin partai yang kurang bersimpati kepada penguasa militer dipaksa keluar dari kedudukan mereka di partai. Golkar benar-benar memonopoli kampanye dan kancah perpolitikan tanah air kala itu.
Kampanye PNI dan NU
Partai lain yang melakukan kampanye adalah PNI. Kampanye yang dilakukan oleh PNI menimbulkan ketegangan antara PNI dan pemerintah. Sebelumnya, anggota PNI sempat kesal dengan pemerintah karena ikut campur dalam pemilihan ketua umum.
Ketua Umum PNI Hadisubeno yang sebelumnya disangka tunduk pada pemerintah, ternyata melakukan kampanye yang mengundang kewaspadaan. Kampanye Hadisubeno bersemangat anti-Golkar dan menyatakan kedekatan hubungan antara PNI dengan Soekarno. Padahal saat itu, ada larangan dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) tentang penyebaran ide-ide Soekarno. Hadisubeno menantang pemerintah untuk membubarkan PNI kalau larangan tersebut diberlakukan.
Dalam pidatonya, Hadisubeno bahkan dengan berani mengatakan, “Sepuluh Soeharto, sepuluh Nasution, dan segerobak penuh jenderal tidak akan dapat menyamai satu Soekarno”. Walaupun sudah berusaha melakukan kampanye dengan penuh semangat, usaha Hadisubeno untuk ikut dalam pemilu akhirnya gagal. Menurut Sejarawan R. William Liddle, Hadisubeno meninggal sebelum pemilu dilaksanakan pada April 1971. Kampanye PNI pun jadi berantakan lantaran ditinggal mati ketua umumnya dalam waktu dua bulan sebelum pemilu.
Sementara itu, nasib Parmusi juga tidak beda jauh dengan PNI. Sebagai partai baru sepertinya Parmusi tidak tahu cara melakukan kampanye sehingga kampanye yang mereka lakukan juga berantakan. Lalu, NU sendiri melakukan kampanye yang penuh semangat dan tetap menjadi partai yang tunduk kepada pemerintah. NU mengeluarkan fatwa bahwa orang Islam wajib memberikan suara kepada partai-partai Islam. Dari total tiga partai besar hanya NU yang tidak menyerang pemerintah secara langsung.
Panggung Dangdut di Era Orde Baru
Di masa yang sama, ketika musim kampanye pemilu tiba, masyarakat lebih sering dijadikan objek untuk menyaksikan pidato para juru kampanye (jurkam). Di saat para jurkam sibuk menebar janji-janji politik, massa yang hadir hanya menjadi pendengar saja. Atau bahkan tak jarang berjingkrak-jingkrak di bawah panggung. Tapi biasanya, kampanye-kampanye tersebut juga menghadirkan biduan-biduan lokal dengan lantunan lagu dangdut.
Era Reformasi
Era Reformasi datang seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah cukup maju. Era di mana masing-masing orang dimulai dari anak-anak hingga orang tua sudah memiliki gawai atau gadget untuk mengakses media sosial. Hal ini menyebabkan penambahan metode kampanye yang mengandalkan kemajuan teknologi. Sehingga partai-partai politik di era eformasi juga sudah mulai memaksimalkan peran serta media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya.
Kampanye di media sosial sekarang ini dapat menggiring opini publik para penggunan media sosial. Alhasil, muncul peran baru sebagai buzzer. Salah satu peran buzzer partai politik atau pasangan calon pemimpin tertentu pastinya melakukan “gencatan gerilya” di jagat maya dengan tujuan tertentu. Media The Guardian pada 23 Juli 2018 pernah mengungkap soal peran buzzer dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Salah satu hal yang diungkap The Guardian adalah soal pasukan maya rahasia yang menyebarkan pesan dari akun media palsu untuk mendukung Ahok. Mereka harus memiliki lima akun Facebook, lima akun Twitter dan satu Instagram untuk menjalankan operasinya di media sosial. Sebagai tambahan, metode kampanye yang ternyata masih bertahan sejak era Orde Lama sampai era Reformasi saat ini adalah saling sindir antar partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.
Amien menyebut saling sindir antar partai politik menjelang Pemilu ternyata memang sudah biasa terjadi sejak Pemilu 1955. Kala itu, ternyata partai-partai politik peserta pemilu juga saling sindir dan ejek. “(Saya) sudah mengalami Pemilu sejak tahun 1955, saat itu umur saya 11 tahun, sudah kelas 6 SD,” kata Amien usai mengikuti tahapan coklit Pemilu 2019, di kediamannya Jalan Pandean Sari, Condongcatur, Depok, Sleman, Jumat, 27 April 2018.
“Saya melihat bagaimana waktu itu partai-partai itu kadang-kadang ketika kampanye saling sindir dan maksimum saling ejek, terutama Masyumi dengan PKI waktu itu. Waktu itu ada empat partai besar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI.”
Meski begitu, Amien mengatakan bahwa aksi saling sindir dan ejek tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak sampai berujung dengan kekerasan fisik. “Tapi lihat tidak ada cerita waktu itu bentrok fisik, indah sekali, tidak pernah ada ‘jotosan’. Itu pengalaman kita sebagai bangsa berdemokrasi.”