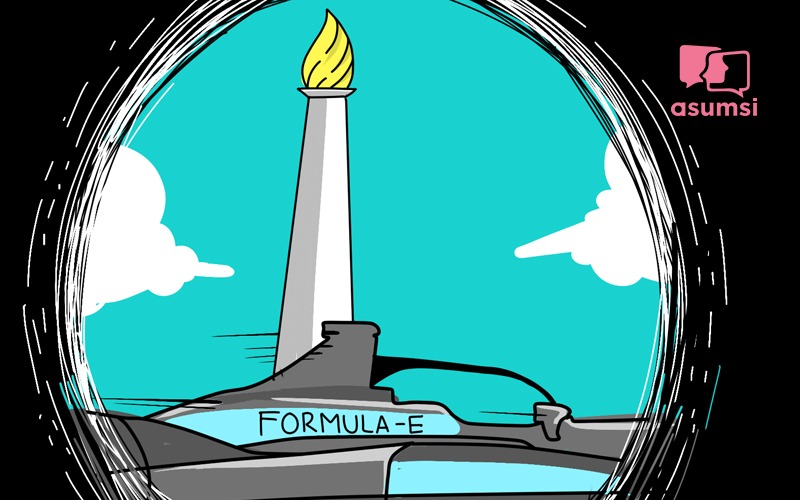Mengapa Kita Ngotot Menggelar Formula E & MotoGP? Sportswashing
Pada malam-malam tertentu, ruas jalan di hadapan Monas akan ditutup dan muda-mudi resah akan menenteng motor mereka untuk balapan. Tujuh bulan dari sekarang, hasrat menggilas aspal tersebut akan semakin terpenuhi. Pada 6 Juni 2020, balapan mobil internasional Formula E akan diselenggarakan di Jakarta. Sesuai dengan ciri khas kejuaraan tersebut, puluhan mobil bakal berjibaku di sirkuit pusat kota. Pemprov DKI Jakarta lekas mempersiapkan anggaran senilai triliunan rupiah demi mempersiapkan daerah sekitar Monas untuk balapan tersebut.
Tentu, Formula E bukan satu-satunya proyek olahraga ambisius yang akan diselenggarakan di Indonesia. Belum lama ini, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah kejuaraan sepakbola Piala Dunia U-20 edisi 2021. Di Nusa Tenggara Barat, Sirkuit Internasional Mandalika tengah dibangun untuk menyongsong kejuaraan motor MotoGP 2021. Demi menyokong proyek raksasa tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabarnya menyediakan anggaran Rp 1,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur pendukung.
Komitmen Indonesia untuk unjuk gigi di ranah olahraga tak mentok di sana. Baru-baru ini, pembalap mobil blasteran Australia, Luis Leeds, kopi darat dengan Menpora Zainudin Amali. Kepada Menpora, Luis meminta dukungan pemerintah agar ia dapat dinaturalisasi jika jadi bertanding dalam ajang Formula One (F1), rencananya pada edisi 2021. Menpora pun menyambut baik permintaan Luis, seraya berjanji pihaknya akan memberi dukungan serta “memfasilitasi apa yang kita bisa fasilitasi”.
Pastinya, semua ini bukan inovasi sekejap dari pikiran-pikiran jenial anggota Kabinet Indonesia Maju. Dengan satu atau lain cara, Indonesia telah lama berupaya menarik perhatian dunia melalui prestasinya di dunia olahraga–meski tentu hasilnya tak selalu sesuai harapan. Ambil contoh Sirkuit Mandalika. Sekarang proyek mentereng tersebut memang kian jadi buah bibir, tapi sesungguhnya ia basian dari proyek era Soeharto yang mangkrak sekian dekade.
Indonesia pun tidak sekali-dua kali mengirimkan perwakilannya ke ajang motorsport. Pembaca Asumsi yang sudah agak uzur mungkin ingat partisipasi Indonesia dalam A1 Grand Prix, balapan mobil yang dijuluki “Piala Dunia Motorsport”. Pada musim pertama di 2006/07, Ananda Mikola mencatatkan posisi menengah ke bawah di klasemen dan beberapa kali mencetak poin. Alamak, prestasi tim Indonesia berangsur-angsur memburuk di musim-musim berikutnya sampai-sampai tiap balapan A1 terasa seperti sadomasokisme berkepanjangan.
Alangkah malangnya pula nasib Doni Tata Pradita, bocah ajaib yang sempat ikutan balapan motor Grand Prix World Championship kelas 250cc. Harapan bahwa ia dapat meniru Sete Gibernau dan sukses bikin jengkel Valentino Rossi pupus saat kami sadar ia dibebani oleh mesin yang jelek dan pengalaman yang minim. Pada 2016, harapan lain muncul saat Rio Haryanto menjadi pembalap Indonesia pertama yang berlaga di F1. Namun setelah hanya 12 balapan bersama tim Manor dan tak satupun poin dicetak, ia mendadak mundur.
Drama terkait cabutnya Rio Haryanto dari ajang F1 adalah preseden menarik. Tiap pembalap mesti menyetor dana dalam jumlah tertentu kepada timnya, dan Rio gagal melunasi hutang sebanyak tujuh juta euro kepada tim Manor. Dana pribadi Rio yang ditomboki uang sponsor Pertamina rupanya tak cukup. Menpora saat itu, Imam Nahrawi, sempat mengajukan ke DPR agar sebagian dana APBN dialihkan demi membiayai Rio, tetapi upayanya gagal. Aroma deja vu jelas menguar saat menyaksikan Menpora saat ini berjanji “memfasilitasi” upaya Luis Leeds menembus Formula One.
Narasi “mengharumkan nama bangsa” memang minta ampun klisenya, tetapi ada alasan riil di balik istilah tersebut. Keberhasilan menjadi tuan rumah ajang olahraga kelas dunia dan segudang “prestasi anak bangsa” lainnya meningkatkan kredibilitas serta citra Indonesia dalam percaturan global. Hal inilah yang disebut ilmuwan politik Joseph Nye sebagai “soft power”, atau kemampuan suatu negara mempengaruhi persepsi serta kebijakan negara lain tanpa mesti menggunakan kekuatan militer. Melainkan melalui kekuatan diplomasi, kebudayaan, dan citra.
Maka ketika kami bilang bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngotot ingin menyelenggarakan Formula E di Ibukota karena gengsi, kami tidak bercanda. Ketika Dino Patti Djalal dari Indonesia Diaspora Network Global mengaku ia memboyong Luis Leeds dan blasteran berprestasi lainnya karena presiden ingin mereka “tampil mempromosikan Indonesia”, ia bersungguh-sungguh. Soft power tak hanya membuat Indonesia makin cemerlang di mata dunia. Ia menjadikan kita tampak seperti rekanan yang kredibel untuk berbisnis dan melakukan kerjasama bilateral.
Secara teori, soft power dapat dihimpun melalui banyak sumber–mulai dari musik, film, kesenian, hingga keberadaan universitas-universitas kelas dunia. Namun, salah satu lumbung soft power yang paling sering dikuras adalah olahraga.
Menurut British Council, menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga tingkat mancanegara dapat menjadi ajang efektif untuk “memamerkan pencapaian dan nilai-nilai suatu negara”, sekaligus “menunjukkan bahwa ia mampu mengelola proyek skala besar.” Lembaga yang bertanggungjawab mengelola diplomasi budaya Britania Raya tersebut memberi contoh dampak positif pasca London menjadi tuan rumah Olimpiade 2012. Pasca Olimpiade, Britania Raya dianggap sebagai tempat yang lebih menarik untuk studi, berbisnis, dan berwisata.
Sayangnya, ajang olahraga pun sering dipakai oleh negara-negara otoriter untuk melunakkan citra buruknya di mata dunia. Saking umumnya praktik tersebut dijalankan, Amnesty International merumuskan istilah baru untuk menggambarkannya: sportswashing.
Menurut akademisi César Jiménez-Martínez & Michael Skey (2015), olahraga kerap digunakan rezim otoriter sebagai bentuk diplomasi budaya sebab kejuaraan olahraga terbebas dari konotasi politik. Hal ini tentu berbeda dengan prestise yang didapat saat menjadi tuan rumah kegiatan seperti Konferensi Asia-Afrika, misalnya, yang sudah jelas embel-embel politiknya. Kejuaraan olahraga di atas kertas tampak netral secara politis dan menarik bagi wisatawan asing. Tak heran bila Martinez dan Skey menyebut sportwashing sebagai bentuk “politically avoiding the political”.
Pasalnya, semua upaya mempolitisir atau memprotes ajang olahraga bakal bungkam ketika kejuaraan tersebut sungguh-sungguh dimulai. Tak sedikit yang memprotes dana yang dihambur-hamburkan untuk Piala Dunia di Afrika Selatan dan Brasil, tetapi suara sumbang tersebut surut seketika ketika pertandingan pertama dimulai. Kritik terhadap tindakan represif rezim Vladimir Putin pun seolah ditunda sejenak sampai Piala Dunia 2018 usai. Gampangnya, tidak ada yang mau merusak suasana pesta pora. Rezim otoriter pun dapat dengan leluasa mempromosikan dirinya melalui ajang olahraga tersebut.
Di sepakbola, misalnya, negara-negara dengan rekor HAM mengkhawatirkan silih berganti mengakuisisi tim-tim mentereng. Pemerintah Qatar, misalnya, secara tidak langsung menjadi pemilik Paris Saint-Germain, mensponsori Bayern Munich dan AS Roma, serta memiliki proyek “yayasan” bersama Real Madrid. Maskapai penerbangan asal Uni Emirat Arab pun mensponsori Real Madrid dan menjadi pemilik Manchester City.
Tak mentok di jazirah Arab, perusahaan minyak Gazprom yang dimiliki pemerintah Rusia pun mensponsori Schalke 04. Hingga kini, Chelsea pun dimiliki seorang taipan asal Rusia yang dikenal dekat dengan rezim Vladimir Putin. Selama lima tahun terakhir, Rusia dua kali menjadi tuan rumah turnamen olahraga kelas dunia. Pada 2014, ia menyelenggarakan Olimpiade Musim Dingin di Sochi. Kemudian pada 2018, Rusia jor-joran demi menjadi tuan rumah Piala Dunia.
Tetangga Rusia, Azerbaijan, juga menggelontorkan dana tak sedikit demi mempromosikan negaranya ke dunia. Pada musim 2013/14 dan 2014/15, mereka menjadi sponsor seragam Atletico Madrid dengan slogan dramatis “Azerbaijan: Land of Fire”. Klub divisi dua Inggris, Sheffield Wednesday, dan tim papan tengah asal Perancis, RC Lens, juga sempat disponsori oleh kampanye Land of Fire. Musim lalu, Azerbaijan menjadi tuan rumah final Piala Europa yang dijuarai Chelsea setelah memecundangi Arsenal dengan skor 4-0.
Kasus Azerbaijan patut ditelisik lebih jauh. Diktator mereka, Ilham Aliyev, tak tanggung-tanggung melakukan sportswashing selama satu dekade terakhir. Bermodalkan fulus dari cadangan gas dan minyak bumi yang melimpah, mereka membangun serangkaian proyek infrastruktur ambisius dan ngebet ingin jadi tuan rumah ajang olahraga. Mereka menjadi tuan rumah European Games 2015, mencalonkan diri untuk jadi tuan rumah Olimpiade 2016 dan 2020, menjadi tuan rumah Youth Olympic Festival 2019, dan akan jadi penyelenggara paling tidak empat pertandingan dalam kejuaraan sepakbola Euro 2020.
Arab Saudi pun tengah menjalankan proyek serupa. Ambisi mereka untuk menjadi pemain besar dalam bidang teknologi termaktub dalam program Vision 2030 yang mentereng. Tetapi, Pangeran Mohammed bin Salman pun mencanangkan strategi sportswashing yang “agresif”. Seperti dicatat The Guardian, pada November 2016 pemerintah Arab Saudi memprakarsai Sports Development Fund yang rencananya akan mendanai pembangunan infrastruktur dan pengembangan olahraga di negara tersebut.
Putri Reema bint Bandar Al Saud, presiden Saudi Federation for Community Sports, juga berulangkali melobi penggede-penggede olahraga Amerika Serikat untuk memulai kerjasama. Sejak 2016, perwakilan Putri Reema berjumpa dengan komisioner Major League Soccer (MLS), Major League Baseball (MLB), juga petinggi dari National Basketball Association (NBA), World Wrestling Entertainment (WWE), hingga komite Olimpiade Los Angeles.
Kehadiran Putri Reema–presiden perempuan pertama organisasi olahraga mentereng tersebut–punya fungsi ganda. Tak hanya meningkatkan kredibilitas pemerintah karena ia anggota keluarga kerajaan Saud, kehadiran seorang perempuan sebagai perwakilan resmi Arab Saudi pun melunakkan imej kerajaan tersebut yang sebelumnya dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Sejak Sports Development Fund dicanangkan pada 2016, Arab Saudi telah menjadi tuan rumah balapan Race of Champions (ROC), pertarungan WWE, pertandingan tinju yang melibatkan Amir Khan, hingga kejuaran golf PGA European Tour.
Namun, kenapa negara-negara ini ikhlas mengeluarkan dana miliaran dollar hanya demi mengembangkan soft power-nya? Sederhana saja: uang.
Baik Arab Saudi maupun Azerbaijan hampir sepenuhnya bergantung pada pemasukan dari sumber daya alam seperti minyak bumi atau gas alam. Persoalannya ada dua: pertama, sumber daya alam seperti itu suatu saat nanti akan habis cadangannya. Kedua, permintaan pasar untuk sumber daya alam seperti minyak bumi diprediksi akan turun drastis dalam beberapa dekade. Selama ini, mereka adem ayem dan citra buruknya ditoleransi karena, mau bagaimanapun juga, semua orang butuh minyak. Kalau minyak habis, lantas mau apa?
Melalui program Vision 2030, Arab Saudi memutuskan untuk mulai menjajaki kemungkinan di ranah teknologi. Adapun dengan kampanye Land of Fire, Azerbaijan ingin mengembangkan industri pariwisatanya. Persoalannya, tak ada orang yang mau berwisata, apalagi berbisnis dengan negara yang dianggap kejam, hobi menindas rakyatnya, dan mengerikan.
Rezim Aliyev di Azerbaijan konsisten di-ranking sebagai salah satu negara dengan rekor HAM terburuk di dunia. Sedangkan Arab Saudi citranya sedang terpuruk di mata dunia akibat keterlibatan mereka dalam peperangan yang brutal di Yaman, serta pembunuhan kejam terhadap jurnalis Jamal Khashoggi yang kabarnya diperintahkan oleh keluarga Saud.
Rusia pun punya pledoi serupa. Invasi mereka terhadap Krimea, keterlibatan terus menerus mereka dalam konflik berkepanjangan di Ukraina, hingga dukungan tak langsung mereka terhadap perang di Suriah semua adalah bagian dari strategi geopolitik mereka. Hal itu penting sebab selama ini, kartu as mereka adalah minyak bumi dan gas alam mereka.
Negara-negara Eropa hampir sepenuhnya bergantung pada pasokan minyak bumi dari Rusia. Ketika kartu as tersebut diproyeksi bakal lepas dari tangan, mereka harus cari kuasa di ranah lain. Demi mengimbangi persepsi buruk komunitas global terhadap mereka, Rusia tak tanggung-tanggung mendanai Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi dan Piala Dunia 2018.
Kita dapat berdebat sampai tahun depan soal etika praktik sportswashing. Persoalannya, apakah ia efektif?
Seperti yang sempat kami sebut di atas, British Council memang sempat menyatakan bahwa Olimpiade 2012 meningkatkan persepsi positif dunia terhadap Britania Raya. Namun itu kasus Britania Raya. Meskipun mereka saat ini sedang terlibat dalam komedi berkepanjangan bernama Brexit, tetap saja mereka negara demokratis yang sudah punya nama mentereng sejak lama. Britania Raya mengejar soft power, tapi mereka tidak sportswashing. Kasus mereka tentu tak sebanding dengan Arab Saudi, Rusia, atau Azerbaijan, yang mesti membangun reputasi dari nol dan sengaja menggunakan olahraga untuk mengalihkan perhatian dunia dari kebijakan represif mereka.
Bagi akademisi Melissa Tandiwe Myambo (2018), sportswashing memang memberikan dampak jangka pendek berupa meningkatnya reputasi serta dampak jangka panjang berupa hadirnya infrastruktur pendukung yang baik. Namun, jika negara tersebut tidak sungguh-sungguh berupaya mengendurkan represi dan melindungi hak-hak orang di negaranya, dampak sesungguhnya dari sportswashing patut dipertanyakan.
Ada satu kritik yang konsisten dilayangkan terhadap upaya sportswashing: dana yang dialirkan buat menyelenggarakan ajang olahraga tersebut seharusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar publik. Hal itulah yang menjadi dasar dari demonstrasi terhadap Piala Dunia di Brasil dan Afrika Selatan, misalnya.
Dalam kasus Formula E di Jakarta, kita mulai melihat terjadinya persoalan serupa. Dana triliunan rupiah untuk Formula E, serta fakta bahwa keseluruhan dana tersebut akan diambil dari APBD dan tidak dari sponsor, diprotes oleh fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Muncul tudingan–yang kemudian disanggah Pemprov–bahwa demi membiayai Formula E, Pemprov mengalihkan dana ratusan miliar yang seharusnya dipakai untuk merenovasi gedung sekolah.
Pada akhirnya, soft power tak akan berarti banyak jika negara tersebut masih saja represif dan menindas rakyatnya sendiri. Joseph Nye, pencipta istilah soft power, menyatakan bahwa Rusia “gagal memanfaatkan Olimpiade dan Piala Dunia” untuk mendongkrak soft powernya. Sebab, mau bagaimanapun juga, mata dunia masih tertuju pada tindakan keji rezim Putin di Ukraina, Suriah, dan di tanah airnya sendiri.
Jika Formula E, MotoGP, Piala Dunia U-20, dan serangkaian proyek ambisius lainnya jadi diselenggarakan di Indonesia, serangkaian pekerjaan rumah menanti kita. Proyek infrastruktur sebesar itu tentu akan mensyaratkan terjadinya penggusuran besar-besaran terhadap warga lokal, perusakan terhadap alam, hingga pengeluaran dana publik yang tak sedikit. Pertanyaannya, apakah Indonesia sekadar berusaha mengejar soft power, ataukah kita sedang sportswashing?