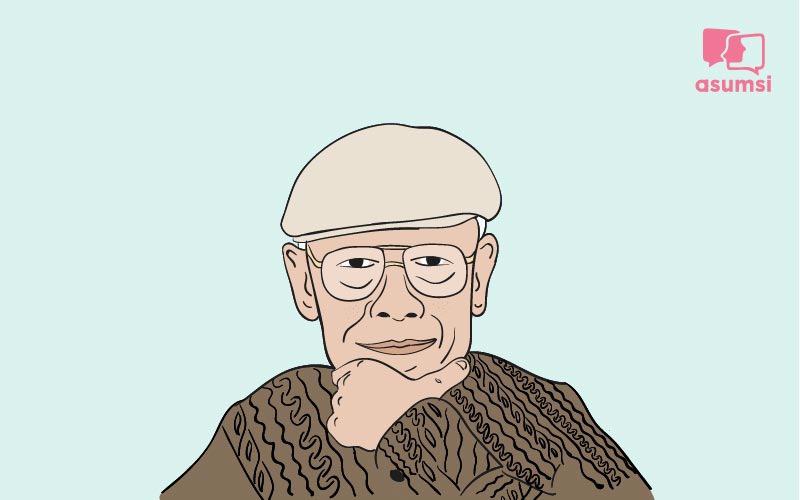Mengenal Pramoedya: Panduan Buat Millennials Sebelum Nonton ‘Bumi Manusia’
Novel sastra legendaris Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer akan segera diangkat ke layar lebar, dengan salah satu pemerannya adalah Iqbaal Ramadhan yang dipercaya sebagai tokoh sentral, Minke. Tapi, seberapa jauh sih kalian mengenal sosok Pramoedya?
Sosok Pram, sapaan akrabnya, tak ujug-ujug heboh dalam sepekan terakhir hanya karena adanya Iqbaal, eks member Coboy Junior dan si pemeran Dilan itu. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, nama Pram melegenda di ranah sastra Indonesia.
Mirisnya, ternyata memang masih ada yang enggak tahu siapa itu Pram dan hal itu terbukti saat munculnya kegaduhan di jagat maya beberapa waktu lalu. Ada seorang netizen, yang entah pengen tenar atau memang polos, dengan santainya mempertanyakan siapa sosok Pram itu?
“Lagian Pramoedya itu siapa sih? Cuman penulis baru terkenal kayaknya… masih untung dijadiin film, dan si Iqbal mau meranin karakternya.. biar laku bukunya,” tulis netizen yang tak diketahui identitasnya tersebut.
[askMF] ada yang tau atau suka sama Pramoedya Ananta Toer? coba comment thought on this pic.twitter.com/4yoQaYbnM2— askMF (@askmenfess) May 27, 2018
Kalimat screenshoot-an yang berasal dari seorang netizen yang tidak diketahui namanya itu mendadak viral beberapa waktu lalu setelah di-posting ulang oleh akun Twitter @askmenfess pada Minggu, 27 Mei, lalu.
Well, di zaman yang serba digital saat ini, tampaknya tak terlalu susah untuk googling dengan dua jempol, lalu mencari kata kunci ‘Pramoedya Ananta Toer’. Tapi, kalau memang masih ada yang malas, yuk kita cari tahu bareng-bareng soal sosok Pram.
Siapa Pramoedya Ananta Toer?
Pram dianggap sebagai salah satu penulis terbesar Indonesia. Ia juga dikenal secara luas karena cerita hidupnya, yang meski pernah mendekam di balik jeruji besi, namun tak membuat pemikirannya terpenjara sampai melahirkan sejumlah karya besar.
Pram yang lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 6 Februari 1925 silam itu, merupakan pahlawan gerakan antikolonial, seorang pejuang hak asasi manusia, dan sosok yang berjuang dalam hal kebebasan berbicara.
Ayah Pram merupakan seorang guru sekolah berjiwa nasionalis yang menginspirasinya untuk bergabung dengan perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Sementara ibunya berasal dari keluarga Muslim yang saleh.
Pram muda pernah bergabung dengan pejuang antikolonial melawan Jepang semasa Perang Dunia II dan kemudian terdaftar dalam pasukan yang melawan penjajah Belanda.
Pram menempuh pendidikan di Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya. Soal pendidikan, Pram sendiri sebenarnya tak pintar-pintar amat, apalagi ayahnya pernah menganggap dirinya sebagai anak bodoh.

Alasan itulah yang membuat sang ayah akhirnya enggan mendaftarkannya ke MULO (setingkat SLTP). akhirnya, Pram pun melanjutkan pendidikan di Sekolah Telegraf (Radio Vakschool) Surabaya atas biaya ibunya.
Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia.
Pram Pernah Dipenjara Selama 3 Periode Berbeda
Pada 1947, Pram ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda. Sejak hidup dan tinggal di penjara itulah, Pram mulai terjun ke dalam dunia tulis menulis atau saat menginjak usia 24 tahun.
Penjara menjadi tempat yang akrab dengan kehidupan yang dilalui Pram. Tak tanggung-tanggung, Pram pernah mencicipi sunyinya kehidupan di balik jeruji besi dalam tiga periode pemerintahan sekaligus; zaman Belanda, Orde Lama, dan Orde Baru.
Dari tiga masa pemenjaraannya tersebut, Pram dikurung dengan berbagai alasan pula. Yang pertama karena Pram dianggap memiliki keterlibatan dalam pasukan pejuang kemerdekaan pada zaman penjajahan Belanda.
Lalu karena masalah bukunya yang berjudul Hoakiau di Indonesia, sebuah buku yang berisi pembelaan terhadap nasib kaum Tionghoa di Indonesia namun tidak disukai pemerintah Orde Lama).
Kemudian, ia ditahan dan diasingkan ke Pulau Buru, Maluku, selama 14 tahun karena dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 oleh rezim Orde Baru, yang dijalani tanpa melewati proses peradilan.
Meski begitu, sekali lagi, penjara dan pengasingan tak membuat pemikirannya terpenjara. Di dalam penjara dan pengasingan itulah, Pram berhasil melahirkan sejumlah karya besarnya seperti Tetralogi Buru dan juga roman Arus Balik.
Bahkan, novel pertamanya yang berjudul Perburuan ditulis dan dihasilkan Pram saat dua tahun masa penahanannya.
Bebas dari Penjara di 1949
Setelah mendekam di penjara, Pram akhirnya dibebaskan pada 1949 dan sejak saat itulah Pram mulai lebih aktif dan produktif lagi dalam menulis buku.
Lalu pada 1950-an, Pram tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya, dan ketika kembali ke Indonesia ia bergabung dan menjadi anggota Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra), salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia.
Didirikan atas inisiatif D.N. Aidit, Nyoto, M.S. Ashar, dan A.S. Dharta pada 17 Agustus 1950, Lekra mendorong seniman dan penulis untuk mengikuti doktrin realisme sosialis. Lekra disebut berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Lalu, gaya penulisan Pram berubah selama masa itu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam karyanya berjudul Korupsi, fiksi kritik pada pamong praja yang jatuh di atas perangkap korupsi. Namun, hal itu justru memunculkan friksi antara Pramoedya dan pemerintahan Soekarno.
Selama masa itu pula, Pram mulai mempelajari penyiksaan terhadap Tionghoa Indonesia. Kemudian pada saat yang sama, ia pun mulai berhubungan erat dengan para penulis di Tiongkok.
Khususnya, ia menerbitkan rangkaian surat-menyurat dengan penulis Tionghoa yang membicarakan sejarah Tionghoa di Indonesia, berjudul Hoakiau di Indonesia.
Pada 1960-an, Pram kembali dipenjara, karena pandangan pro-Komunis Tiongkoknya. Dalam hal ini, Pram juga dianggap menyoroti diskriminasi dan penindasan terhadap minoritas di Indonesia.
Kenapa Pram Dibuang ke Pulau Buru?
Saat Pram ditahan, buku-bukunya dilarang dari peredaran, dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusakambangan di lepas pantai Jawa.
Ketika Jenderal Soeharto berkuasa atas kudeta tahun 1965, ia memerintahkan penangkapan resmi atas ratusan ribu lawan politiknya dan Pram kembali ditangkap pada tahun 1965 selama kudeta militer.
Selama masa Orde Baru sendiri, Pram merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Rinciannya adalah pada 13 Oktober 1965 – Juli 1969, Juli 1969 – 16 Agustus 1969 di Pulau Nusakambangan, Agustus 1969 – 12 November 1979 di Pulau Buru, November – 21 Desember 1979 di Magelang.
Pram dikirim ke pulau terpencil, Pulau Buru pada tahun 1969 tersebut karena dicurigai terkait dengan komunis.
Di masa Orde Baru sendiri, Pulau Buru sudah menjadi semacam camp untuk mengirim musuh atau lawan politik pemerintah. Pekerja seni, pelajar, wartawan, pekerja bidang lain yang dianggap kiri dan terlibat G 30 S dibuang ke Pulau Buru.
Selama masa penahanannya di Pulau Buru, Pram dilarang menulis. Awalnya, ia tidak diberikan pena dan kertas yang bisa digunakannya untuk menulis, jadi dia menceritakan kisahnya pada sesama tahanan.
Meski begitu, Pram tetap mengatur untuk menulis serial karya fenomenalnya yang berjudul Bumi Manusia, bagian dari Tetralogi Buru atau serial 4 kronik novel semi-fiksi sejarah Indonesia.
Dalam novel Bumi Manusia, tokoh utamanya adalah Minke, bangsawan kecil Jawa, dicerminkan pada pengalaman RM Tirto Adisuryo, seorang tokoh pergerakan pada zaman kolonial yang mendirikan organisasi Sarekat Priyayi dan diakui oleh Pramoedya sebagai organisasi nasional pertama.
Esai dan surat-suratnya yang ditulis selama periode itu diterbitkan dalam sebuah memoar, The Mute’s Soliloquy namanya.
Apa Saja Karya Pramoedya?
Sepoeloeh Kepala Nica (1946), hilang di tangan penerbit Balingka, Pasar Baru, Jakarta, 1947; Kranji – Bekasi Jatuh (1947), fragmen dari Di Tepi Kali Bekasi; Perburuan (1950), pemenang sayembara Balai Pustaka, Jakarta, 1949 (dicekal oleh pemerintah karena muatan komunisme).
Keluarga Gerilya (1950); Subuh (1951), kumpulan 3 cerpen; Percikan Revolusi (1951), kumpulan cerpen; Mereka yang Dilumpuhkan (I & II) (1951); Bukan Pasar Malam (1951); Di Tepi Kali Bekasi (1951), dari sisa naskah yang dirampas Marinir Belanda pada 22 Juli 1947.
Dia yang Menyerah (1951), kemudian dicetak ulang dalam kumpulan cerpen; Cerita dari Blora (1952), pemenang karya sastra terbaik dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, Jakarta, 1953; Gulat di Jakarta (1953).
Midah Si Manis Bergigi Emas (1954); Korupsi (1954); Mari Mengarang (1954), tak jelas nasibnya di tangan penerbit; Cerita Dari Jakarta (1957); Cerita Calon Arang (1957); Sekali Peristiwa di Banten Selatan (1958); Panggil Aku Kartini Saja (I & II, 1963; bagian III dan IV dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965.
Kumpulan Karya Kartini, yang pernah diumumkan di berbagai media, dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965; Wanita Sebelum Kartini dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965.
Gadis Pantai (1962-65) dalam bentuk cerita bersambung, bagian pertama triologi tentang keluarga Pramoedya; terbit sebagai buku, 1987, dilarang Jaksa Agung, jilid kedua dan ketiga dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965.

Sejarah Bahasa Indonesia. Satu Percobaan (1964), dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965; Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia (1963); Lentera (1965), tak jelas nasibnya di tangan penerbit.
Bumi Manusia (1980), dilarang Jaksa Agung, 1981; Anak Semua Bangsa (1981), dilarang Jaksa Agung, 1981; Sikap dan Peran Intelektual di Dunia Ketiga (1981);
Tempo Doeloe (1982), antologi sastra pra-Indonesia.
Jejak Langkah (1985), dilarang Jaksa Agung, 1985; Sang Pemula (1985); dilarang Jaksa Agung, 1985; Hikayat Siti Mariah, (ed.) Hadji Moekti, (1987); dilarang Jaksa Agung, 1987; Rumah Kaca (1988), dilarang Jaksa Agung, 1988.
Memoar Oei Tjoe Tat, (ed.) Oei Tjoe Tat, (1995), dilarang Jaksa Agung, 1995; Nyanyi Sunyi Seorang Bisu I (1995); dilarang Jaksa Agung, 1995; Arus Balik (1995); Nyanyi Sunyi Seorang Bisu II (1997).
Arok Dedes (1999); Mangir (2000); Larasati (2000); Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2005).
Kenapa Bukunya Pernah Dilarang Pemerintah Orde Baru?
Sejak era Orde Lama, ada UU No. 4 tahun 1963 yang membuat Kejaksaan Agung punya “hak” untuk melarang peredaran buku dan semua barang cetakan yang dianggap bisa mengganggu ketertiban umum.
Sebenarnya, DPR tidak mengesahkan UU tersebut, namun Soekarno tetap menjalankan peraturan itu dengan menjadikannya sebagai penetapan Presiden. Aturan itu akhirnya diteruskan oleh Orde Baru.
Novel-novel fenomena dalam Tetralogi Buru karya Pram seperti Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, pernah dilarang dibaca dan beredar oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Misalnya saja, setelah diterbitkan, Bumi Manusia kemudian dilarang beredar setahun kemudian atas perintah Jaksa Agung. Sebelum dilarang, buku ini sukses mengalami 10 kali cetak ulang dalam setahun pada rentang 1980-1981.
Saat itu, pemerintah menganggap novel-novel karya Pram tersebut berisi propaganda ajaran-ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme, meski sebenarnya tak satupun dari paham itu disebutkan dalam bukunya.
Tak hanya empat novel itu, ada puluhan dan setidaknya mencapai total 24 judul novel karya Pram yang saat itu juga dicekal.
Buku-buku itu seperti Hoakiau di Indonesia, Keluarga Gerilya, Perburuan, Mereka yang Dilumpuhkan, Pertjikan Revolusi, Keluarga Gerilja, Ditepi Kali Bekasi, Bukan Pasar Malam, Tjerita Dari Blora, Midah si Manis Bergigi Emas, Korupsi, Gulat di Djakarta, Tjerita dari Djakarta, Sekali Peristiwa di Banten Selatan, Panggil Aku Kartini Sadja jilid 1 & 2.
Kapan Pramoedya Wafat?
Pada 27 April 2006, Pram sempat tak sadarkan diri. Pihak keluarga akhirnya memutuskan membawanya ke RS Saint Carolus di Salemba, Jakarta Pusat, hari itu juga.
Saat itu, Pram didiagnosis menderita radang paru-paru, penyakit yang selama ini tidak pernah menjangkitinya, ditambah komplikasi ginjal, jantung, dan diabetes. Akhirnya Pram meninggal dunia di ibu kota, Jakarta, pada 30 April 2006 pada usia 81 tahun.