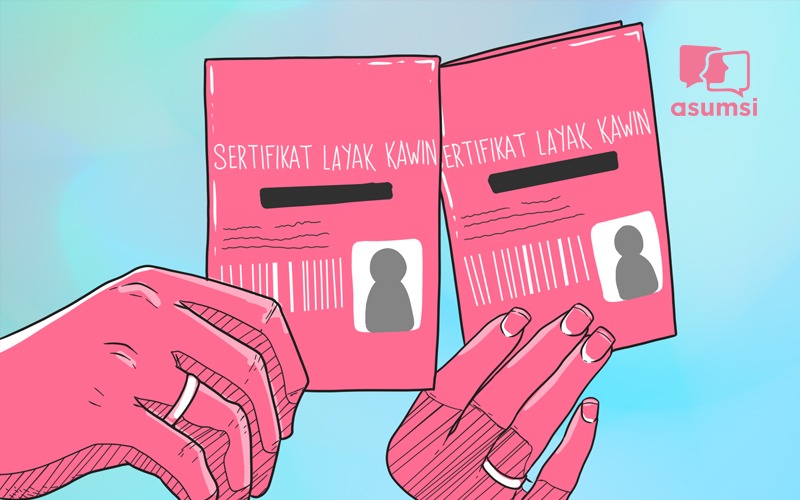Kursus Pranikah: Diperkosa Suami Yes, Dipoligami Yes?
“Anda kan mau nikah, nih. Anda mau [berhubungan seks], nih. Dia [istri] nggak mau. Kalau gitu caranya gimana? Ceraikan ajalah.”
“Kalau dia [istri] sedang haid, atau dia baru saja melahirkan, tapi Anda mau [berhubungan seks], boleh. Tapi tidak memasukkan ke vaginanya. Di bagian lain. Di sela-sela lain. Ya silakanlah.”
“Jadi yang dikeluhkan oleh teman saya itu, dia pulang. Yang dibayangkannya adalah goler-goler [berbaringan] di tempat tidur. Bukan doa [istri]nya, bukan ngajinya. Suaminya sudah pulang, sudah malam. Isya sudah lewat. Lalu suaminya goler-goler di tempat tidur. Istrinya ngaji terus. Bukannya nggak boleh ngaji, nggak boleh sholat, tapi tahu nggak maunya apa? Menari [berhubungan seks], lah.“
Ucapan-ucapan itu disampaikan oleh seorang pemateri kursus pranikah di Pekanbaru, Riau, pada awal Januari lalu. Sebagai calon pengantin, Marsya dan Yudis (bukan nama sebenarnya) mengikuti kursus pranikah selama dua hari berturut-turut—dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 atau 4 sore. Kursus tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Masing-masing dari mereka mesti membayar iuran sebesar Rp150.000 untuk mengikuti kursus tersebut.
Namun, materi yang disampaikan di kursus bersebrangan jauh dengan ekspektasi mereka. “Ada sesi yang topiknya adalah ‘finansial dalam rumah tangga’. Kan gue kayak, oh, gue akan diajarin tentang mengatur keuangan. Tapi isinya ternyata kayak, ‘suami harus cari duit biar istri bisa belanja, sementara tugas istri adalah menafkahi suami dengan seks.’ Jadi kewajiban istri itu adalah ngangkang dan di-ewe aja gitu,” kata Yudis kepada Asumsi.co (20/2).
Marsya berkata sebagian besar materi yang disampaikan di kursus membuatnya tidak nyaman. Komentar dan candaan seksis dilontarkan oleh pemberi materi dan disambut tawa serta persetujuan oleh kebanyakan peserta laki-laki.
Selama dua hari tersebut, kebanyakan materi yang disampaikan menyudutkan perempuan sebagai istri. “Perempuan selalu dipojokkan, sementara laki-laki tidak ikut dipersiapkan. Misalnya soal beretika dalam rumah tangga, yang di-point out duluan adalah bagaimana istri melayani suami,” kata Marsya kepada Asumsi.co (21/2). Tanggung jawab suami memang tetap disinggung. “Tapi itu selalu di bagian akhir dan porsinya sedikit,” lanjut Marsya.
Sepanjang kursus tersebut, ada tiga poin utama yang paling sering ditekankan pemateri. Pertama, suami punya wewenang untuk berhubungan seksual dengan istri kapan saja, bahkan ketika istri tidak mau. “Ada ustad yang ngomong di pernikahan itu tidak ada pemerkosaan. Karena itu memang hak suami,” tutur Marsya.
Kedua, menyalahkan tingginya angka perceraian terhadap perempuan sebagai istri–terutama istri yang bekerja. “Di Pekanbaru itu angka perceraiannya tinggi banget, dan rata-rata yang meminta itu perempuan yang bekerja. Jadi hampir semua materi menganjurkan perempuan untuk di rumah aja,” ujar Marsya.
Ketiga, soal poligami. Para peserta kursus dipaksa untuk menyetujui praktik poligami. “Yang perempuan dipaksa untuk berteriak, ‘saya setuju poligami.’”
Tak hanya di Pekanbaru, materi kursus pranikah di salah satu KUA di Jakarta juga tidak jauh berbeda. Cahaya dan Langit (juga bukan nama sebenarnya) mengikuti kursus pranikah di salah satu KUA Jakarta Selatan pada akhir Januari lalu. Berbeda dengan Marsya-Yudis, kursus pranikah yang mereka jalani berlangsung satu hari, mulai pukul 8 hingga 12 siang.
“Yang paling kuingat, ada perkataan dari pemateri yang intinya, ‘istri tinggal nggak pake celana dalam aja pas tidur, tinggal slep [penetrasi alat kelamin].’ Jangan harap ada kesetaraan [gender] deh di materi yang mereka tulis,” ujar Cahaya kepada Asumsi.co (19/2).
“Aku paling nggak tahan dengan pandangan pematerinya. Istri, yang mata duitan, harus selalu melayani suami. Tugas istri di rumah, sementara suami cari uang,” kata Langit kepada Asumsi.co (20/2).
Kedua pasangan ini diwajibkan untuk mengikuti kursus pranikah. “Supaya si KUA itu mau menikahkan kami, mengeluarkan buku nikah buat kami, kami mesti menyerahkan sertifikat pranikah terlebih dahulu—yang kami nggak bisa dapet kalau kami nggak ikut kursusnya,” jelas Yudis.
“Sifatnya wajib, udah diwanti-wanti sama penghulunya untuk ikut karena hasilnya adalah sertifikat,” kata Cahaya.
Patriarkis Sejak dalam Undang-undang
Menurut Cahaya-Langit dan Marsya-Yudis, materi kursus pranikah banyak bersandar pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam salah satu sesi materi pranikah yang diikuti oleh Marsya dan Yudis, terdapat presentasi yang memaparkan pasal-pasal dalam UU tersebut. Begitu pula dalam lembar formulir bernama “Naskah Penasehatan Calon Pengantin” yang meminta calon pasangan untuk menjabarkan poin-poin dalam UU yang mereka ketahui.
Undang-undang tentang perkawinan tersebut mengatur definisi perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, dan lain-lain. Pasal 4 ayat (2), misalnya, mengatur bahwa suami diperbolehkah menikah dengan lebih dari satu perempuan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan.
Pasal 31 ayat (3) menyebut “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Begitu pula dengan Pasal 34 yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”
Aktivis kesetaraan gender Tunggal Pawestri mengatakan isi UU No. 1 Tahun 1974 sudah tidak relevan. “Itu kan sudah outdated. Tahun 1974 gitu, ya. Dulu, nilai-nilai patriarch masih sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Tapi pendidikan soal keadilan gender dan situasi ekonomi yang sudah berubah seharusnya juga mengubah relasi antar manusia—termasuk perempuan dan laki-laki,” kata Tunggal kepada Asumsi.co (21/2).
Tunggal juga menyayangkan materi kursus pranikah yang berpandangan bahwa perceraian semata disebabkan kesalahan perempuan. “Perempuan akhirnya semacam diminta untuk menginternalisasi nilai-nilai itu,” kata Tunggal.
Banyak perempuan yang bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan atau beracun. Korban KDRT sering kali mudah memaafkan pasangannya, berharap pasangannya akan berubah, atau merasa tak cukup berharga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan, banyak perempuan yang menyalahkan diri sendiri atas perilaku kekerasan yang dilakukan pasangannya. Hasil penelitian Perempuan Mahardhika tentang KDRT pada buruh perempuan, misalnya, menunjukkan bahwa sebagian korban KDRT enggan menuntut cerai karena merasa hanya suami selaku imam yang dapat menceraikan istri, hingga kepercayaan bahwa bertahan dalam hubungan pernikahan adalah pintu menuju surga.
“Ini lagi-lagi soal ketimpangan gender. Bagaimana perempuan dianggap sebagai pihak yang seharusnya merawat. Jadi, ketika ada sebuah kegagalan, itu dianggap ketidakmampuan perempuan untuk merawat. Stereotip semacam ini sebenarnya yang harus diakhiri. Sudah nggak bisa lagi dilanggengkan,” ujar Tunggal.
Tunggal sepakat pendidikan pranikah diperlukan—bahwa ada pembekalan yang mesti diberikan kepada pasangan yang hendak menikah. “Yang harus disampaikan kan sebenarnya hak-hak istri, hak-hak suami. Dikasih tau pula soal KDRT, apa yang bisa dilakukan oleh suami dan istri jika terjadi KDRT. Lalu informasi tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, edukasi seks,” kata Tunggal.
“Saya nggak yakin apakah orang yang memberikan pelatihan itu orang yang cukup punya kompetensi untuk memberikan pelatihan. Ini yang yang perlu diperhatikan.”
Perombakan Materi Kursus Pranikah
Materi kursus pranikah yang diikuti oleh Marsya dan Yudis diisi oleh lima orang, empat di antaranya adalah ustad atau pemuka agama, dan satu orang adalah dokter. “Dalam dua hari, masing-masing pengisi materi memberikan pernyataan yang saling bertentangan,” tutur Marsya.
“Di akhir sesi, ada tes yang sifatnya formalitas. Ada pertanyaan seperti, ‘berapa lama jeda antara kehamilan?’ Kalau mengikuti pernyataan ustad yang pertama, jawabannya secepat mungkin. Kalau mengikuti pernyataan dokter, jawabannya minimal dua tahun. Jadi malah menimbulkan kebingungan.”
Ketua Tim Penyusun Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Kementerian Agama, Alissa Wahid, mengaku materi kursus pranikah masih tidak merata, tidak seragam, dan kerap menyudutkan perempuan. Sebab, masih banyak materi kursus pranikah yang bergantung pada perspektif masing-masing petugas KUA-nya.
“Iya, yang pendekatannya misoginis, ya. Isi materi yang istri nggak punya posisi yang sama dengan suami, suami boleh memaksa istri, kayak gitu-gitu. Itu benar-benar tergantung pada perspektif penghulunya,” kata Alissa kepada Asumsi.co (20/2).
Sejak tahun 2017, Alissa dan timnya di Kemenag berusaha mengikis praktik tersebut dengan membuat materi model baru bernama bimbingan perkawinan. “Kalau model dulu itu kan kamu diceramahin. Tapi kalau sekarang itu modelnya workshop. Di versi baru ini, ada aktivitas bersama yang dilakukan oleh calon suami istri. Tujuannya agar hubungan suami istri itu bisa lebih adil dan nggak dominasi-subordinasi gitu,” kata Alissa.
“Dua hari itu isi workshop-nya mulai dari pondasi keluarga sakinah, memperkenalkan perspektif keadilan antara suami istri, membicarakan financial planning, kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, cara berkomunikasi dan menangani konflik, kayak gitu,” lanjutnya.
Namun, model bimbingan perkawinan ini belum tersebar secara merata. Sejak dimulai pada 2017, baru sekitar 1.900-an dari 5.900-an KUA yang mendapatkan pelatihan. Menurut Alissa, hal ini disebabkan oleh anggaran dari pemerintah yang terbatas. “Karena itu, dari 2 juta pasang calon pengantin setiap tahunnya, baru 150 ribu-an pasangan yang bisa mendapatkan fasilitas ini. Itu sebabnya masih banyak praktik yang kayak tadi mbak sebutkan,” tutur Alissa.
Alissa juga membantah kursus pranikah bersifat wajib. “Kalau untuk bimbingan pranikah itu paketnya bukan wajib terus kalau nggak ikut dia nggak boleh nikah. Bukan gitu ya. Jadi tidak ada sertifikasi kemudian menjadi syarat. Itu nggak ada,” kata Alissa.
Namun, hal ini masih bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sebagaimana pernyataan dua pasangan yang bercerita kepada kami. Wacana untuk mewajibkan kursus pranikah juga pernah dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada November 2019 lalu. Tetapi kemudian diklarifikasi menjadi tidak wajib.
“Bahkan rencananya mereka akan melakukan itu selama tiga bulan, bukan dua hari lagi. Setelah tiga bulan baru bisa mendapatkan sertifikat pernikahan,” kata Marsya. “Kalau pun misalnya pemerintah mewajibkan kursus pranikah, diseleksi nggak siapa yang memberi materinya? Disamakan nggak materinya? Karena jangan sampai masing-masing pemateri punya pandangan masing-masing dan bikin calon-calon pasutri ini bingung.”
“Ketika kami sudah bayar untuk belajar, untuk dapat sertifikat itu, tapi yang diberikan itu sangat-sangat traumatik. Bahkan salah satu pemateri nggak sengaja keceplosan bahwa tahun lalu ada yg gagal menikah karena si perempuannya nggak mau [melanjutkan kursus]. Ya, iyalah, siapa yang mau diperkosa sama suami sendiri?” katanya.