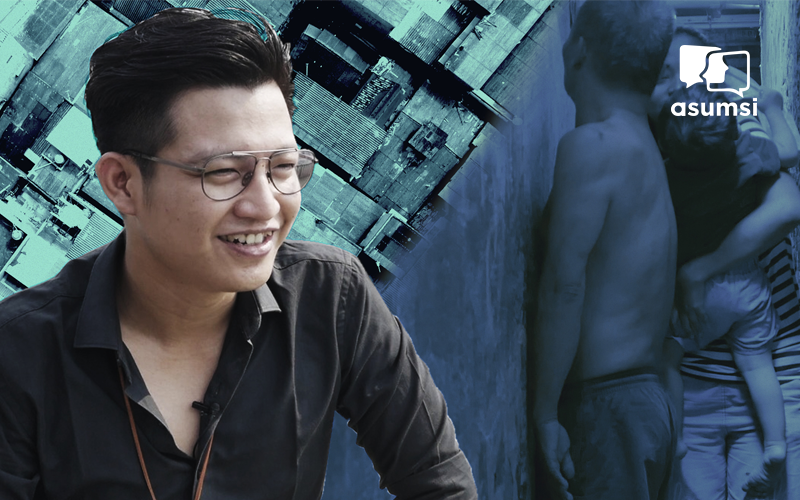Di balik #AsumsiDistrik: Tambora Membara
Sepekan lalu, dua rumah dan enam kios di kawasan Tambora, Jakarta Barat mengalami kebakaran. Kebakaran diduga disebabkan oleh kompor gas warung bakso yang meledak dan kemudian terbakar. Tak main-main, 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 450 juta Rupiah.
Kebakaran jadi bencana yang cukup sering dialami oleh warga Tambora. Setiap bulannya, hampir ada saja kasus kebakaran dengan penyebab bermacam-macam: bensin eceran yang tercecer, listrik korslet, hingga api yang timbul dari gudang penyimpanan kembang api.
Kepadatan penduduk jadi salah satu penyebabnya. Setiap satu kilometer persegi, 50.000 orang tinggal. Dengan bangunan rumah yang begitu berdekatan, jalan yang relatif sempit, hingga bangunan dari kayu dan bahan-bahan mudah terbakar lain, kebakaran jadi tak terelakkan.
Jika kamu mencari Tambora di Google, artikel-artikel yang akan kamu temukan tentang kecamatan ini akan berkaitan dengan “lokasi padat penduduk”, “kebakaran”, dan “biang narkoba”. Istilah kumuh pun jadi terlintas di otak. Namun, benarkah Tambora bisa didefinisikan sekadar sebagai wilayah kumuh?
Asumsi Distrik mengikuti Wahyu, laki-laki berusia 22 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Rumahnya terletak di Kelurahan Kalianyar yang populasinya terpadat se-Tambora. “Ada tiga keluarga yang tinggal di sini,” kata Wahyu, menunjuk rumahnya di ujung gang yang luasnya tak lebih dari 20 meter persegi. Ruang tamunya telah sesak oleh ibu-ibu yang sedang beraktivitas dan anak-anak yang sedang bermain. Menurut Wahyu, rumah tersebut ditinggali setidaknya oleh 11 orang.
Hidup Wahyu mencerminkan hidup-hidup keluarga lain di Kalianyar. Yanto, Ketua RT, mengatakan bahwa hampir tak ada rumah yang hanya dihuni oleh satu keluarga atau satu KK (kartu keluarga). “Yang lima keluarga (di satu rumah) juga ada,” katanya.
Hidup di tengah kesesakan sudah jadi lahapan sehari-hari warga Kalianyar. Selain warga asli, banyak pula pendatang dari luar Jakarta dan Jawa yang memilih Kalianyar, Tambora sebagai wilayah untuk mereka tempati sementara. Kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sanitasi jadi semakin terbatas. Rumah-rumah tak dilengkapi dengan tempat pembuangan air. WC umum dan got jadi tempat mereka untuk mengeluarkan hajat.
Tak dimungkiri bahwa kepadatan penduduk di Kalianyar, Tambora menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tak mudah diselesaikan. Saking tak ada lagi tempat tersisa, misalnya, warga enggan membikin septic tank yang membutuhkan banyak ruang. Namun, tak dimungkiri pula bahwa pemberitaan dan persepsi masyarakat terhadap kawasan Tambora ini seringkali berlebihan.
Banyak media yang mengatakan bahwa setiap 1 meter persegi, kawasan Tambora dihuni oleh empat orang. Ada pula yang mengatakan bahwa warga tidur bergantian di siang dan malam untuk menyiasati luas tempat tinggal yang terlalu sempit. “Bohong itu, berlebihanlah,” kata Yanto.
Tentu, masalah kepadatan itu nyata dan bantuan pemerintah tetap dibutuhkan. Akses terhadap air dan upaya pencegahan kebakaran membutuhkan pemerintah yang punya sumber daya yang cukup untuk menanggulanginya. Tetapi, apakah solusi yang selama ini ditawarkan telah benar-benar solutif? Warga mengeluh pemerintah menggeneralisir Tambora sebagai wilayah yang tercampak, tidak aman, atau tidak layak ditempati. Padahal, masing-masing warga sendiri punya persepsi yang berbeda tentang Tambora. Ada yang memang tak nyaman dan memilih untuk pindah. Ada juga yang merasa baik-baik saja. Berpuluh-puluh tahun tinggal di Tambora, hidupnya tentram dan aman.
“Yang penting nyaman buat makan sehari-hari,” kata salah satu warga. Maka, pemerintah diharapkan untuk lebih sering berdialog dengan warga-warga di sana—bukannya berasumsi dan menyamaratakan solusi untuk setiap warga. Penggusuran dan relokasi, misalnya, acap dianggap solusi terbaik oleh pemerintah untuk membenahi sebuah wilayah. Namun, solusi ini seringkali tak diterima dengan baik oleh orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut.
Tambora pun pernah kena gusur. Beberapa hunian dianggap ilegal, dan warganya dipindahkan ke rumah susun. Padahal, bisa jadi ada pendekatan-pendekatan lain yang baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Devi Rahmawati selaku pengamat sosial mengatakan bahwa kuncinya adalah mendengarkan. “Konsepnya bukan pemerintah datang dan menggurui masyarakat, tetapi bagaimana caranya mendapatkan kepercayaannya dulu,” kata Devie.
Sebagaimana banyak kisah kampung yang terpinggirkan, Tambora adalah tempat untuk bertahan hidup bagi penduduk-penduduknya—seburuk apa pun citranya di mata pemerintah dan orang lain. Kebanyakan warga di Tambora tak sembarang hidup setahun dua tahun di sana. “Saya sudah dari orok tinggal di sini,” kata Wahyu. Maka, mungkin sudah saatnya pula kita mendengarkan mereka yang jauh lebih paham seluk beluk distriknya.
Di tengah gang sempit dan gelap itu, Asumsi Distrik mendengar kisah-kisah warga.