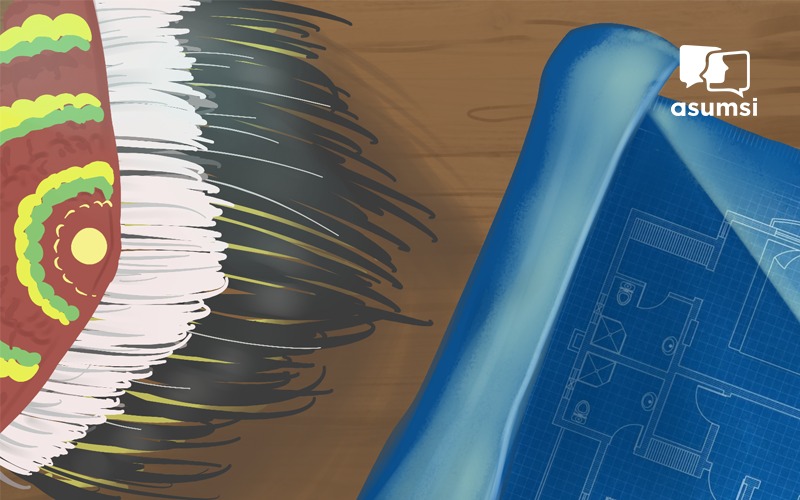Koordinator KontraS Papua: Istana Negara Tidak Menyelesaikan Persoalan
Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan 61 tokoh Papua di Istana Presiden (10/09/19) untuk membahas sejumlah masalah yang terjadi di Papua. Abisai Rollo selaku Ketua DPRD Kota Jayapura menyampaikan sembilan poin aspirasinya kepada Jokowi.
Kesembilan poin ini berkisar pada aspek pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa di antaranya adalah pemekaran provinsi 5 wilayah di Papua dan Papua Barat, Istana Kepresidenan di Jayapura, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di kementerian dan TPMK, serta pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi untuk mahasiswa Papua.
Jokowi menyetujui rencana pemekaran wilayah dan pembangunan Istana Kepresidenan. Abisai Rollo bersedia menghibahkan 10 hektare tanahnya untuk istana. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mengatakan kepada CNN bahwa mereka mempunyai dana cadangan sebesar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar yang bisa digunakan.
“Sehingga perjalanan Bapak Presiden ke Papua berubah dari berkunjung menjadi berkantor di Papua,” ucap Abisai kepada Tribunnews.
Namun, pertemuan 61 perwakilan Papua dan Jokowi ini mengundang protes dari warga Papua sendiri. Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengaku tidak mengetahui pertemuan itu dan mempertanyakan kapasitas 61 orang tersebut dalam mewakili Papua.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Sam Awon, koordinator KontraS Papua.
Sam mengatakan bahwa 61 orang yang diundang oleh Presiden tidak merepresentasikan tokoh-tokoh Papua. “Kami bingung 61 orang yang ketemu Jokowi ini perwakilan dari mana. Kawan-kawan kami dari CSO, NGO, gereja, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak tahu sama sekali dan kaget tentang pertemuan ini,” ujarnya kepada Asumsi (11/9/19).
Sam mengatakan aspirasi-aspirasi yang dibawakan tersebut tidak menyentuh akar masalah konflik Papua. “Tidak perlu membangun gedung-gedung lagi. Papua tidak meminta Istana Negara. Ada trauma dan pelanggaran HAM yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu,” ujar Sam.
Pembangunan Istana Negara dan pemekaran wilayah adalah narasi sejak masa Orde Baru. Di Papua, ada Gedung Negara yang telah dilengkapi dengan kantor kepresidenan. Gedung yang diresmikan pada April 2017 ini mempunyai fasilitas-fasilitas seperti kamar dan ruang tamu presiden, aula, kediaman gubernur, taman, air mancur, landasan helikopter, dan 50 kamera pengintai.
“Gubernur sudah membangun Gedung Negara yang bisa digunakan Jokowi untuk berkantor. Membangun Istana Kepresidenan lagi hanya akan menghabiskan dana negara,” lanjut Sam.
Sementara itu, pemekaran wilayah Papua mengundang pro-kontra sejak penerbitan UU No. 45 Tahun 1999 tentang pemekaran Papua. Dalam penelitian LIPI bertajuk “Pro-kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran bagi Pemerintah Pusat”, dikatakan bahwa rencana pemekaran wilayah Papua tak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Orang-orang daerah ngotot untuk dilakukan pemekaran wilayah di daerah mereka. Tapi, kasus Papua berbeda seratus delapan puluh derajat. Sebab, yang ngotot adalah Pemerintah Pusat,” tutur Lili Romli sebagai peneliti LIPI.
Pro-kontra Rencana Pemekaran dan Penyelesaian Parsial
Penelitian LIPI selama 2004-2011 berjudul “Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present, and Securing The Future” mengelompokkan permasalahan di Papua menjadi empat hal: marjinalisasi dan diskriminasi masyarakat Papua, kegagalan pembangunan, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan sejarah politik ketidakpercayaan terhadap Papua
Untuk menyelesaikan persoalan ini, LIPI merekomendasikan empat poin utama yang harus dilakukan oleh pemerintah: (1) mengakui diskriminasi dan marjinalisasi yang dialami orang Papua, (2) mengubah paradigma pembangunan menjadi berorientasi pada pemenuhan hak dasar warga Papua pada bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan publik lain, (3) melakukan dialog dengan masyarakat Papua, serta (4) melakukan rekonsiliasi dengan cara menyingkap perilaku kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara terhadap warga Papua.
Namun, menurut LIPI, penyelesaikan konflik di Papua seringkali tidak mempertimbangkan relasi keempat aspek tersebut. “Penyelesaian masalah Papua cenderung dilakukan secara parsial. Padahal, satu masalah dengan masalah lain saling berkorelasi, terutama antara kepentingan politik dan ekonomi,” ujar Lili Romli.
Tentang rencana pemekaran, misalnya, ada perbedaan perspektif antara pemerintah pusat dan penduduk Papua. Menurut penelitian LIPI, pemekaran dianggap oleh warga Papua sebagai upaya untuk memecah belah rakyat. Pemekaran wilayah Papua yang telah terjadi sebelumnya juga hanya dijadikan dalih untuk mendanai fasilitas-fasilitas birokrasi di wilayah-wilayah baru tanpa mementingkan kebutuhan publik.
“Masyarakat menolak karena pemekaran dilakukan berdasarkan kepentingan elit-elit politik di Jakarta, memecah aspirasi Papua, meningkatkan ruang kontrol Pemerintah Pusat terhadap Papua melalui pembentukan Kodim dan Polda di provinsi-provisi baru, dan tidak melibatkan masyarakat Papua—khususnya kalangan adat dan gereja,” tutur Lili. Menurutnya, rencana pemekaran seharusnya dilakukan dengan melibatkan dan memperhatikan keinginan masyarakat daerah.
Menurut Sam, pertemuan 61 tokoh Papua dan Jokowi tidak mencerminkan hal itu. “Orang-orang ini jarang terlibat dalam membangun rekonsiliasi Papua. Sembilan tuntutan tersebut tidak menjawab situasi Papua saat ini dan tidak didasari komunikasi dengan orang-orang yang terpapar konflik. Kami tidak mau menyebut mereka tokoh,” ujar Sam. Pernyataan serupa datang dari Natalius Pigal, mantan komisioner HAM, yang mengatakan bahwa Abisai Rollo tidak mewakili tokoh-tokoh Papua.
Solusi pemekaran dan pembangunan Istana Negara juga tidak sejalan dengan solusi yang ditawarkan oleh LIPI. “Jika tidak mau mendengarkan anjuran pihak-pihak luar, pemerintah seharusnya setidaknya mengikuti apa yang dirumuskan oleh LIPI. LIPI kan termasuk dalam lembaga pemerintah. Diakui oleh negara,” kata Sam melanjutkan.
Diskriminasi dan Rasisme yang Mengakar
Sejak Orde Baru, konflik di Papua kerap ditangani dengan pendekatan militeristik. Laporan Amnesty International Indonesia mencatat 69 kasus dugaan pembunuhuan di luar hukum di Papua selama tahun 2010-2018. Kasus-kasus ini melibatkan polisi, militer, dan Satpol PP. Amnesty International juga telah menerima laporan kasus-kasus serupa sejak tahun 1998.
Merespons demo besar-besaran yang dilakukan warga Papua setelah persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, TNI dan Polri juga mengirimkan 2.529 personel tambahan ke Papua dalam rentang 21-30 Agustus 2019.
“Masyarakat takut beraktivitas sehari-hari karena aparat dengan senjata lengkap masih menguasai jalan-jalan. Mungkin itu aman bagi negara, tapi rakyat yang ingin beraktivitas jadi ketakutan,” kata Sam.
Menurutnya, penyelesaian konflik seharusnya dilakukan dengan mendengarkan suara masyarakat, termasuk LSM, koalisi CSO, dan seruan dari Majelis Rakyat Papua. “Ada pula tokoh-tokoh agama Kristen, Katolik, dan Islam yang telah lama mengabdi dan membangun rekonsiliasi perdamaian di Papua,” tutur Sam.
Gereja-gereja Papua yang tergabung dalam Forum Oikumenis Gereja-gereja Papua menyikapi situasi Papua dengan mengeluarkan Seruan Gembala. Poin-poin yang disampaikan antara lain adalah menyatakan diskriminasi rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, dan Makassar adalah pengulangan tindakan rasisme dan diskriminasi yang kerap dialami orang asli Papua.
Para pimpinan Gereja di Papua juga menyerukan agar: (1) pasukan non-organik TNI dan Polri ditarik dari Papua, (2) membebaskan warga sipil yang sedang ditahan oleh POLRI dalam rangka menegakkan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, (3) meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum kepolisian TNI dan ormas, dan (4) menghukum aparat dan ormas yang melakukan tindakan persekusi kepada Mahasiswa Papua.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan bahwa penangkapan puluhan mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan Manokwari serta Jayapura memperlihatkan bagaimana aparat negara dan kelompok non-negara melakukan diskriminasi rasial kepada warga Papua.
“Apalagi mengingat mahasiswa dalam asrama tidak melakukan aksi perlawanan atau menyerang aparat yang membahayakan jiwa petugas atau orang lain. Kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi di Surabaya. Sayangnya, tidak ada tindakan dari aparat keamanan dan pemerintah setempat untuk menghentikannya,” kata Usman, sebagaimana dilansir CNN Indonesia.
Penyelesaian konflik di Papua seharusnya dilakukan dengan rekonsiliasi dan menindaklanjuti pelanggaran-pelangagran HAM di Papua. Menurut Sam, rekonsiliasi tidak dapat dicapai jika orang-orang yang diundang ke Istana Negara tidak mewakili aspirasi masyarakat Papua. “Negara tidak boleh menciptakan tokoh-tokoh siluman. Mari duduk dan berunding. Pemerintah tidak perlu takut nanti Papua jadi merdeka,” ujar Sam.
Kehadiran orang-orang yang tidak representatif justru akan memperkeruh konflik dan mengadu domba masyarakat. “Sudah terjadi konflik berkepanjangan di Papua, dan ini malah diarahkan ke konflik horizontal antara orang Papua dengan orang Papua. Ini kan justru membuat persoalan menjadi semakin rumit. Kasihan masyarakat Papua. Keluarga dan sanak saudara bisa jadi saling menyerang,” ucap Sam.